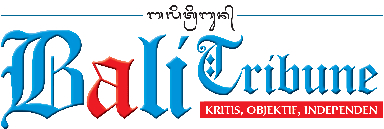Diposting : 10 January 2019 20:22
Hans Itta - Bali Tribune

BALI TRIBUNE - Bisnis esek-esek seperti sulit matinya. Meski sudah ditekan dengan berbagai cara, jaringan prostitusi khususnya yang online masih saja subur. Realitas itu, setidaknya menunjukkan bahwa betapa internet kini tidak lagi sekadar kebutuhan, tetapi juga telah menjadi gaya hidup masyarakat.
Di era serba digital seperti sekarang, hampir segala kebutuhan hidup, termasuk kebutuhan seksual dapat terpenuhi cukup lewat satu sentuhan jari di layar ponsel. Era digital memang telah memperluas praktik prostitusi. Jika dahulu prostitusi hanya dapat ditemukan di ruang-ruang fisik tertentu, kini para penikmatnya bisa ‘bertamasya’ di dunia prostitusi secara daring.
Banyak cara untuk mengakses prostitusi secara online, di antaranya dengan memanfaatkan aplikasi pertemanan, forum komunitas, hingga aplikasi pesan. Konon, salah satu aplikasi pertemanan yang paling terkenal di dunia prostitusi online, adalah Twitter. Lewat aplikasi itu, cukup mengetikkan sejumlah kata kunci (keyword) tertentu untuk menemukan akun yang menawarkan jasa prostitusi online.
Kasus prostitusi online yang melibatkan artis VA dan FA yang ditangkap di sebuah hotel di Surabaya, Sabtu (5/1) pekan silam, sejatinya bukan hal mengejutkan. Sebab, sebelumnya, tahun 2015, publik sempat geger dengan terungkapnya sindikat prostitusi online di mana pekerja seksnya berprofesi sebagai model dan publik figur. Dari muncikari, Robby Abbas, didapatkan daftar siapa saja model dan publik figur yang 'dijual' ke lelaki hidung belang, beserta daftar harganya yang fantastis.
Robby pun divonis hukuman penjara 1 tahun 4 bulan karena terbukti melanggar Pasal 296 KUHP, yakni melakukan perbuatan mempermudah orang lain berbuat cabul dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Sementara itu, sederet model dan publik figur yang berada dalam daftar Robby, dinyatakan bebas.
Kini, publik kembali dihebohkan dengan kasus serupa. Kali ini melibatkan seorang model sekaligus pembawa acara di televisi berinisial VA.
Sama seperti kasus Robby dan AA, Polisi menahan dua orang muncikari. Sementara, VA dan seorang rekannya sesama artis berinisial AS dibebaskan serta dilabeli sebagai korban dan status sebagai saksi. Adilkah?
Sebetulnya Polisi perlu menahan diri dalam menangani kasus prostitusi online. Mengumbar identitas dan visual dalam kasus VA dan AS di Surabaya yang ditangkap di sebuah hotel, Sabtu pekan lalu, merupakan tindakan yang kelewatan.
Sejak awal penyidikan, polisi seolah-olah menempatkan kedua selebritas itu sebagai pelaku utama. Hal ini menyalahi aturan karena obyek utama dalam delik prostitusi adalah muncikari. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat menjerat pekerja seks, juga pengguna jasanya. Hal itu terbukti dengan dilepaskannya VA dan AS setelah diperiksa berjam-jam. Mereka diberi status sebagai saksi dan korban.
Sebaliknya, peran ES dan TN, germo yang disebut mendapat 30 persen dari nilai transaksi, seperti tenggelam. Padahal, merekalah aktor yang sesungguhnya. Mereka dijerat dengan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP yang berkaitan dengan tindak memudahkan perbuatan cabul dan mencari keuntungan dari pelacuran.
Polisi seperti tidak belajar dari kasus sebelumnya. Saat menangani kasus muncikari prostitusi online Robbi Abbas, yang mencuat pada Mei 2015, nama-nama selebritas yang diduga terlibat dalam jaringan prostitusi online seolah menenggelamkan penanganan kasus itu sendiri.
Polisi seharusnya belajar dari Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK berulang kali menangani kasus pelacuran perempuan sebagai bagian dari gratifikasi seksual. Namun mereka tak genit mengumbar identitas pekerja seks dan berfokus pada penuntasan kasus utama.
Kasus VA dan AS di Surabaya ini menarik untuk menjadi pelajaran. Di kalangan pegiat isu-isu gender dan hak asasi manusia (HAM) sendiri, mereka terpecah soal ini. Ada yang menyebut VA dan AS sebagai korban. Mereka dianggap sebagai korban perdagangan orang, eksploitasi orang dekat, atau jeratan muncikari. Namun ada juga pegiat isu-isu gender dan HAM, seperti Tunggal Pawestri, yang menyebutkan bahwa VA dan AS bukanlah korban. Itu karena perempuan seperti VA berdaulat atas tubuhnya. Artinya, ia berhak untuk melakukan apa yang ia mau atas tubuhnya karena VA dan AS bukanlah korban human trafficking yang tak punya kuasa.
Apa pun pendapat soal VA yang membuka tarif Rp80 juta sekali kencan, dan AS yang mematok tarif Rp25 juta, yang pasti ekspose polisi yang berlebihan membuat VA dan AS dua kali menjadi korban. Jejak digital akan menempatkan mereka sebagai pekerja seks selamanya. Ini merupakan hukuman yang jauh lebih berat ketimbang hukuman untuk muncikari.
Sementara media juga turut bersalah. Dalam hitungan jam setelah penangkapan, nama lengkap serta foto VA dan AS menempati spot berita terbaru dan utama. Koran-koran menempatkan berita itu pada cover depan dan mengeksploitasinya pada hari berikutnya.
Sudut pandang yang mendominasi dalam pemberitaan adalah semua hal tentang si figur publik. Padahal banyak sudut pandang yang bisa dikupas dan lebih bermanfaat bagi kepentingan umum, misalnya, siapa aktor utama, kemungkinan aparat yang menjadi beking, dan mengapa polisi seperti membidik VA. Sudut pandang berita soal muncikari dan R, pengusaha pengguna jasa seks, baru muncul setelah banjir cerita korban reda.