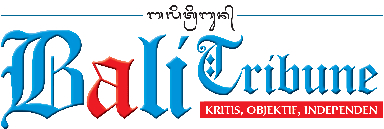Diposting : 2 August 2018 09:12
habit - Bali Tribune

Oleh: Ignas Kleden
BALI TRIBUNE - Bahasa Indonesia telah diresmikan sebagai bahasa nasional, sedangkan bahasa itu diambil dari bahasa Melayu Riau yang sejak berabad-abad berfungsi sebagai lingua franca. Kita tahu, suatu bahasa menjadi lingua franca kalau bahasa itu digunakan sebagai sarana komunikasi tetapi tidak berperan lagi sebagai penunjuk identitas suatu kelompok orang.
Seseorang yang fasih berbahasa Inggris dewasa ini, tidak dengan sendirinya berasal dari San Fransisco atau Liverpool. Atau seorang profesor yang memberi kuliah dalam bahasa Spanyol tidak harus berasal dari Madrid. Inilah rupanya sebab yang jarang diungkapkan, mengapa bahasa Melayu dengan mudah diterima sebagai bahasa nasional karena bahasa itu tidak lagi menjadi representasi suatu identitas etnis tertentu, dan telah menjadi sarana komunikasi di antara berbagai kelompok etnis sejak ratusan tahun.
Lain halnya kalau bahasa Jawa, bahasa Sunda atau bahasa Bugis diusulkan sebagai bahasa nasional. Mungkin timbul lebih banyak kontroversi dan pertentangan karena bahasa-bahasa besar itu menunjuk dan menjadi penanda suatu identitas etnis tertentu, yang mungkin sekali menimbulkan penolakan dari kelompok etnis lainnya.
Atas cara yang sama kita bisa berbicara tentang nilai-nilai publik. Apabila suatu komunitas budaya hendak menyumbangkan seperangkat nilai-nilainya ke dalam kehidupan publik, maka atribut-atribut dan nomenklatur komunal perlu dihilangkan (tanpa menghilangkan substansi nilai yang dikandungnya) agar supaya nilai tersebut dapat dipahami dan diterima oleh kelompok lainnya, karena nilai publik itu telah menjadi suatu nilai bersama meskipun nilai-nilai itu telah lahir dan dikembangkan dalam suatu komunitas budaya tertentu.
Etos kapitan perahu yang secara tradisional berlaku di daerah-daerah pesisir di Sulawesi, dilegitimasi oleh nilai-nilai budaya setempat, dan legitimasi itu dilaksanakan karena alasan-alasan sosial atau kosmologis yang berhubung dengan kebudayaan setempat.
Namun demikian substansi etos itu dapat dibawa ke ruang publik, dan dapat diusulkan sebagai alternatif terhadap budaya politik Indonesia, yang umumnya diambil dari latarbelakang daerah pertanian. Kecenderungan kepada pola kepemimpinan feodal, atau hubungan patron klien dalam politik Indonesia, jelas berasal dari latar belakang masyarakat dan kerajaan-kerajaan yang berdasarkan pertanian.
Sebagai alternatif terhadap kecenderungan tersebut etos kapitan perahu dapat diusulkan ke dalam diskusi dalam ruang publik, setelah segala alasan budaya yang menjadi dasar dari etos tersebut dan setelah nomenklatur yang bersifat komunal ditanggalkan. Karena pada dasarnya substansi etos itu – sekali pun tanpa disertai alasan-alasan budaya yang bersifat komunal — dapat diterapkan dalam politik Indonesia, sebagai negara dengan sifat maritim yang kuat.
Ahli sejarah maritim, Prof. Adrian B. Lapian, pernah mengeritik penamaan Indonesia sebagai negara kepulauan, karena nama itu tidak menunjukkan aspek laut yang merupakan bagian terbesar dari negeri ini. Istilah kepulauan masih memperlihatkan orientasi ke daratan, sedangkan istilah negara kelautan lebih tepat menunjukkan watak negeri ini sebagai kawasan maritim.
Istilah ‘negara kepulauan’ merupakan padanan dalam bahasa Indonesia dari pengertian archipelagic state. Jika kita menyimak arti sesungguhnya dari kata archipelago, maka (menurut kamus Oxford dan Webster) kata ini berasal dari bahasa Yunani yakni arch (besar, utama) dan pelagos (laut). Jadi archipelagic state sebenarnya harus diartikan sebagai ‘negara laut utama’ yang ditaburi dengan pulau-pulau, bukan negara pulau-pulau yang dikelilingi laut. Dengan demikian paradigma perihal negara kita seharusnya terbalik, yakni negara laut yang ada pulau-pulaunya.
Dalam kaitan dengan negara kelautan, maka etos kapitan perahu dapat menunjukkan orientasi baru dalam budaya politik Indonesia. Pertama, dalam etos kapitan perahu, seorang pemimpin perahu tidak mungkin didrop begitu saja dari atas, tetapi harus bertumbuh dari bawah dan mencapai pengetahuan dan kematangan tertentu yang dipersyaratkan.
Dropping tentu saja bisa dilakukan, akan tetapi risikonya akan sangat tinggi, karena kapitan perahu yang tidak menguasai pengetahuan tentang navigasi, alur pelayanan, arah angin, tanda badai, cara menetapkan arah perahu dengan membaca letak bintang, tidak akan sanggup membawa perahu dan penumpangnya sampai ke tempat tujuan, atau perahunya segera menabrak karang dan tenggelam. Ibaratnya, dia harus membawa perahunya dari Surabaya ke Makasar, tetapi perahunya terdampar di Cilacap.
Kedua, dalam etos ini diharuskan proses pengambilan keputusan yang cepat dan kemampuan mengoreksi keputusan dalam waktu singkat. Ketika menghadapi topan di tengah laut seorang kapitan perahu tidak bisa mengajak berunding para awak dalam musyarawarah selama dua tiga jam.
Dia harus memutuskan dengan cepat, misalnya pada pukul 23.00 malam, dan kemudian kalau keputusannya terbukti keliru, dia harus mengoreksinya pada pk. 23.05. Keragu-raguan dalam mengambil keputusan, dan kelambanan atau keengganan untuk mengoreksi keputusan yang salah akan berakibat fatal bagi keselamatan perahunya dan hidup para penumpang perahu.
Ketiga, dalam menghadapi bahaya karamnya perahu maka seorang kapitan perahu akan menjadi orang terakhir yang meninggalkan perahu, setelah penumpang lain mendapat kesempatan menyelamatkan diri atau mendapat pertolongan yang semestinya.
Secara tradisional dia dilarang meninggalkan perahunya apabila masih ada penumpang yang membutuhkan pertolongan. Tentu saja seorang kapitan perahu bisa juga ketakutan menghadapi bahaya dan dapat meluputkan dirinya sebelum penumpang lainnya selamat. Akan tetapi hal itu akan merupakan aib yang diceritakan turun-temurun di kampung halamannya, dan turunannya harus menanggung malu untuk waktu yang lama, karena ada kapitan perahu yang demikian pengecut menyelamatkan diri sambil meninggalkan penumpang perahu terkatung di tengah laut, dihempas ombak dan meninggal ditelan badai.