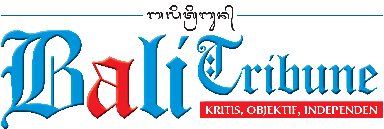Passang Rinpoche Akan Pimpin Ribuan Umat dalam Prosesi Chau Tu dan Yen Kung
BALI TRIBUNE - Ribuan orang akan ikut kegiatan upacara Chau Tu dan Yen Kung di Vihara Satya Dharma, Denpasar pada Sabtu (10/11) mendatang.
Keluarga Besar FBC Sambut Kedatangan YM Passang Rinpoche
BALI TRIBUNE - Menggunakan pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID-6516, Yang Mulia Passang Rinpoche kali kedua mendarat di Bandara Ngurah Rai, Bali pukul 19.51 Wita penerbangan Jakarta-Denpasar, Kamis (8/11).
“Jalan Hindu”
BALI TRIBUNE - Hari Suci Galungan telah berlalu, sebentar lagi Hari Raya Kuningan menjelang. Sebelum, kedua Hari Suci Hindu itu didahului Hari Natal ‘milik’ Umat Nasrani. Bali dengan mayoritas pemeluk Agama Hindu, tidak pernah punya masalah dengan rentetan hari raya keagamaan yang bersinggungan seperti itu. Semuanya baik-baik saja.
Polda Bali Musnahkan BB Narkoba Senilai Rp23,5 M
balitribune.co.id I Denpasar - Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Adityajaya memimpin pemusnahan barang bukti Narkotika hasil sitaan Polda Bali dengan nilai jual mencapai harga Rp23,5 miliar bertempat di depan Loby Ditresnarkoba, Mapolda Bali, Rabu (4/3/2026).
Perkuat Komitmen Pembangunan Ruang Terbuka Hijau, Bupati Resmikan Lapangan dan Taman Desa Adat Angantaka
balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa meresmikan Lapangan dan Taman Desa Adat Ida I Gusti Ngurah Gde Abian, Desa Adat Angantaka, Abiansemal, Selasa (3/3). Peresmian yang bertepatan dengan Rahina Purnama Sasih Kesanga tersebut ditandai dengan pemotongan pita oleh Bupati sebagai simbol difungsikannya fasilitas publik bagi masyarakat Desa Angantaka.
Kasanga Festival 2026 Siap Digelar, 16 Besar Ogoh-Ogoh Akan Ikuti Pawai dan Suguhkan Penampilan Kesenian
balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar kembali akan menggelar Kasanga Festival (Kasangafest) ke-4 pada 6 - 8 Maret 2026 di kawasan Catur Muka dan Lapangan Puputan Badung. Tak seperti tahun lalu, pelaksanaan parade ogoh-ogoh dilakukan dengan sistem parade seperti peed aye saat Pesta Kesenian Bali (PKB). Selain itu, Kasanga Festival tahun ini difokuskan pada penampilan seni, tanpa ada konser musik.
7 Proyek Vila Melanggar, Komisi I Rekomendasikan Penghentian Paksa
balitribune.co.id I Tabanan – Komisi I DPRD Tabanan merekomendasikan penghentian paksa tujuh proyek pembangunan vila liar di Desa Kaba-Kaba dan Desa Cepaka, Kecamatan Kediri.
Ketujuh proyek vila milik investor luar daerah itu disetop pengerjaannya karena mencaplok sempadan sungai dan melanggar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
Sidak MBG di Jegu, Komisi IV Temukan Menu Tanpa Susu
balitribune.co.id I Tabanan - Komisi IV DPRD Tabanan kembali menemukan ketimpangan komposisi menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SDN 2 dan 3 Jegu, Kecamatan Penebel, Rabu (4/3/2026).
Pemkot Denpasar Ajak Seluruh Stakeholder Jaga Keamanan, Kondusifitas dan Kelancaran Rangkaian Hari Suci Nyepi
balitribune.co.id | Denpasar - Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama menjaga keamanan, kondusifitas dan kelancaran Rangkaian Hari Suci Nyepi Caka 1948 Tahun 2026. Rangkaian tersebut dimulai dari Pelaksanaan Prosesi Makiyis/Melasti, Tawur Agung Kesanga, Malam Pangerupukan, Nyepi dan Ngembak Geni.