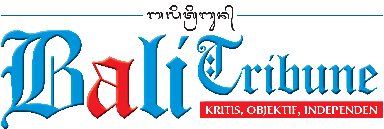balitribune.co.id | “LPD has given new strength to the desa pakraman, and has provided inclusive access to financial services for everyone in the customary village" (LPD telah memberikan kekuatan baru kepada desa pakraman, dan menyediakan akses jasa keuangan yang inklusif bagi setiap orang di desa adat). (H. Seibel)
Bulan Agustus dua tahun yang lalu, saya diminta jadi pembicara oleh Forum Peduli Adat Bali dalam seminar dan lokakarya (semiloka) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dari sudut pandang Konstitusi. Kali ini saya kembali diminta memberi “pidato intisari” (keynote speech) ihwal pokok bahasan yang sama. Pada kesempatan ini, saya tidak akan mengulangi materi yang saya sampaikan dua tahun itu melainkan cukup melampirkannya sebagai bagian tak terpisahkan dari keynote speech ini.
Kalau saya memberi judul tulisan ini “Sekali Lagi: Lembaga Perkreditan Desa”, itu karena saya sungguh-sungguh berharap hanya sekali ini saja saya berbicara kembali tentang LPD. Setelah ini, moga-moga tidak ada lagi seminar, simposium, lokakarya, atau bentuk “forum ilmiah” apapun yang membicarakan LPD – dalam konteks status hukum maupun landasan konstiusionalnya dalam UUD 1945. Artinya, setelah seminar ini, semoga tidak ada lagi masalah yang tersisa berkait dengan keberadaan LPD, khususnya perbedaan pandangan di kalangan masyarakat Bali sendiri.
Sebab, bagi saya, semua hal yang berkait dengan status hukum dan landasan konstitusional LPD sudah jelas. Tinggal bagaimana mengimplementasikannya dalam praktik sehingga membawa sebesar-besar manfaat bagi masyarakat Bali. Maka, sebagaimana halnya harapan para pengurus LPD yang tak ingin ada pengutangnya menunggak angsuran, saya pun tak ingin menunggak cicilan materi pembicaraan tentang LPD.
“Utang” untuk memberikan ulasan keberadaan LPD dari perspektif konstitusi telah saya bayar lunas dua tahun lalu. Oleh karena itu, apa yang akan sampaikan berikut lebih merupakan tambahan terhadap hal-hal yang belum sempat saya jelaskan pada semiloka tersebut disertai dengan harapan-harapan saya terhadap kelangsungan LPD di masa yang akan datang. Untuk itu, perkenankan saya untuk terlebih dahulu meresumekan kembali pandangan saya pada semiloka dimaksud agar peserta seminar memperoleh sekadar gambaran singkat.
Keberadaan LPD lebih mendapatkan pengakuan sekaligus penguatan secara hukum setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM). Pasal 39 ayat (3) UU LKM menyatakan: Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini.
Ada empat hal yang terkandung dalam materi muatan Pasal 39 ayat (3) UU LKM tersebut, yaitu:
1. Bahwa LPD, Lumbung Pitih Nagari, dan lembaga-lembaga sejenis lainnya yang telah ada sebelum lahirnya UU LKM tetap diakui keberadaannya dan tetap berlaku;
2. Bahwa LPD, Lumbung Pitih Nagari, dan lembaga-lembaga sejenis lainnya yang telah ada sebelum lahirnya UU LKM yang diakui keberadaannya itu adalah lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan hukum adat;
3. Bahwa terhadap LPD, Lumbung Pitih Nagari, dan lembaga-lembaga sejenis lainnya yang telah ada sebelum lahirnya UU LKM yang diakui keberadaannya itu tunduk pada hukum adat; dan
4. Bahwa UU LKM tidak berlaku terhadap LPD, Lumbung Pitih Nagari, dan lembaga-lembaga sejenis lainnya yang telah ada sebelum lahirnya UU LKM yang diakui keberadaannya itu.
Dengan kehadiran Pasal 39 ayat (3) UU LLM tersebut, pembentuk undang-undang bukan hanya berarti mengakui keberadaan hukum adat tetapi secara implisit juga berarti mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat yang membentuk lembaga keuangan yang berdasarkan hukum adat itu, yaitu LPD, Lumbung Pitih Nagari, dan lembaga sejenis lainnya yang telah ada dan dibentuk berdasarkan hukum adat. Hal ini merupakan implementasi sekaligus konkretisasi lebih lanjut ketentuan yang tertuang UUD 1945.
Sebagaimana diketahui, setelah dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat (yang pada zaman Hindu Belanda dahulu disebut rechtsgemeenschap) yang masih hidup mendapat pengakuan dan penghormatan dari negara. Bukan hanya keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum ada itu yang diakui melainkan juga termasuk hak-hak tradisionalnya – yaitu hak-hak yang melekat pada dan merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat tersebut. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan:
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
Dalam analisis lebih jauh, secara implisit atau tidak langsung, ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU LKM juga berarti menegaskan bahwa Desa Adat (Desa Pakraman) adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini penting diberi catatan tersendiri karena banyak (kalau tak hendak dikatakan hampir seluruh) kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia “mati” ketika diberlakukannya Undang-Undang 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, padahal yang diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 adalah kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup. Namun, di Bali, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat tersebut, baik yang bercorak teritorial (misalnya Desa, Banjar) maupun yang bercorak geneologis (misalnya Dadia) tetap hidup.
Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat ini ternyata tidak terpengaruh oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Karena itu, secara konstitusional, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Bali itu memiliki kemampuan hukum (legal capacity) untuk mempertahankan hak-hak tradisionalnya yang diakui berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sepanjang (dan karena dalam kenyataannya) sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, Pasal 39 ayat (3) UU LKM merupakan pengakuan negara terhadap eksistensi Desa Adat (Desa Pakraman) sebab yang membentuk LPD adalah Desa Adat (Desa Pakraman).
Namun, di lain sisi, dengan rumusan Pasal 39 ayat (3) UU LKM di atas, secara a contrario juga terkandung pengertian atau penafsiran bahwa UU LKM, khususnya Pasal 39 ayat (3), tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi pembentukan lembaga-lembaga baru semacam LPD atau Lumbung Pitih Nagari pada masa yang akan datang meskipun lembaga demikian dibentuk berdasarkan hukum adat. Pasal 39 ayat (3) UU LKM semata-mata merupakan rekognisi atau pengakuan terhadap lembaga-lembaga keuangan yang telah ada dan dibentuk berdasarkan hukum adat serta, pada saat yang sama, mengecualikan keberlakuan UU LKM terhadap lembaga-lembaga keuangan yang telah ada yang dibentuk berdasarkan hukum adat itu. (bersambung)