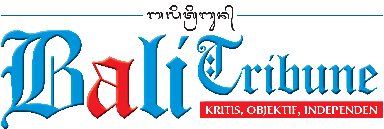Oleh Hans Itta*)
balitribune.co.id | Gema damai di bumi itu sudah dikumandangkan pada 2000 tahun lalu. “Kemuliaan bagi Allah di tempat Yang Maha Tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya” (Luk.2:14). Berita itu untuk pertama kali diperdengarkan kepada para gembala di Betlehem di tanah Yudea berbicara tentang damai di bumi.
Pada malam yang dingin dan hening saat para gembala sedang menjaga kawanan domba di padang Efrata. Kepada mereka disampaikan pesan damai di bumi. Itulah visi Natal. Natal adalah berita damai di bumi.
Pesan damai itu sepertinya tidak relevan dengan keadaan damai tanpa perang saat itu, namun sebenarnya amat relevan dengan tuntutan damai sejati. Yesus lahir semasa Kaiser Agustus berkuasa yang sangat terkenal dengan kebijakan politik Pax Romana. Pada waktu itu Kaiser Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah perdaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Siria
Kaiser Agustus yang ambisius itu melakukan ekspansi besar-besaran dan agresi militer ke Timur dan Barat, sehingga saat meninggalkan daerah kekuasaannya seluas 3.340.000 mil persegi atau seluas dari Amerika Serikat (Yonky Karman: 2010). Karena penaklukannya itu, memang tidak ada perang selama 200 tahun. Kemakmuran, ketertiban, dan stabilitas nasional yang begitu lama belum ada tandingannya dalam sejarah.
Damai tetapi gersang adalah kata lain untuk damai di atas imoralitas, penindasan, dan eksploitasi. Meski Kaiser Agustus bisa memberikan damai tanpa perang di darat dan di laut, ia tidak memberikan damai tanpa hawa nafsu, duka cita, dan rasa iri. Ia tidak mampu memberikan damai di hati, yang dirindukan manusia lebih daripada damai secara lahiriah.
Damai karena tidak ada perang; tidak ada kerusuhan dan aman walau tidak berarti tenteram yang membawa kedamaian.
Damai adalah dambaan manusia kapan dan di mana pun. Damai yang diwartakan pada Natal pertama adalah buah dari pertobatan manusia untuk kembali ke jalan yang benar, lalu manusia berdamai dengan diri sendiri dan sesama. Itulah damai yang memuliakan Tuhan dan dikenhendaki oleh Tuhan Pencipta alam semesta.
Tuhan tidak dimuliakan dalam damai model Pax Romana (kedamaian di bawah kekuasaan Romawi itu terjadi hanya karena penguasa menindas semua perbedaan pendapat), yang dibangun di atas ambisi dan kejahatan politik, oligarki untuk kepentingan sendiri atau kelompok, korupsi, kekerasan, eksploitasi, agama yang tidak memihak kemanusiaan. Walau dikenal sebagai periode kemakmuran terpanjang yang pernah diketahui umat manusia, pencapaian tertinggi dalam sejarah kenegarawanan.
Damai di antara sesama di bumi menjadi komoditas mahal. Perang masih terjadi di berbagai belahan bumi. Perseteruan antar penganut agama juga masih menjadi santapan harian. Dalam konteks Natal bagi umat Kristiani masih menjadi sebuah keprihatinan. Tengok di berbagai belahan bumi masih saja terjadi pelarangan ibadah dan perayaan Natal.
Umat Kristiani di berbagai negara tidak sepenuhnya bebas merayakan Natal untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus. Hal ini terjadi karena ada sejumlah negara yang resmi melarang perayaan Natal diadakan secara terbuka, bahkan ada pemerintah yang resmi menjerat mereka yang merayakan Natal sebagai kriminal.
Pemerintahan kerajaan Brunei Darussalam, misalnya, melarang perayaan Natal digelar secara terbuka. Pohon Natal dan ornamen tidak dibolehkan muncul di ruang publik. Pelanggaran atas aturan ini akan diseret ke pengadilan dan dijebloskan ke penjara hingga 5 tahun lamanya. Menurut pemerintah Brunei, perayaan Natal secara terbuka akan merusak akidah komunitas Muslim di negara itu.
Korea Utara lebih ekstrim lagi. Penguasa Korea Utara bersikap anti Natal yang sangat kuat sehingga mengancam akan menembakkan artileri ke pohon Natal di dekat perbatasan Korea Selatan. Ancaman itu dikeluarkan setelah sekelompok umat Kristen Korea Selatan memajang pohon Natal. Korea Utara menganggap pohon Natal itu sebagai alat perang psikologis.
Somalia di Afrika yang mayoritas Muslim juga melarang perayaan Natal. Natal, katanya, merupakan tindakan ilegal dan tidak sesuai prinsip Islam. Begitu pula di Tajikistan yang mayoritas Muslim memberlakukan aturan melarang pohon Natal.
Begitu juga perayaan Natal secara terbuka dilarang di Saudi. Sebanyak 1,2 juta umat Kristen di Saudi merayakan Natal di tempat-tempat pribadi dan perumahan. Demikian pula di China. Pemerintah Partai Komunis China melarang perayaan Natal di sekolah-sekolah seperti terjadi di salah satu kota di Provinsi Guizhou.
Damai di antara sesama menjadi komoditas mahal. Eskalasi kekerasan horizontal yang dimotori sipil meningkat seiring runtuhnya penguasa Orde Baru. Teror bom menjadi gejala anarki sosial yang semakin biasa. Setelah bom Bali melebar di beberapa tempat dan rumah-rumah ibadah.
Ledakan bom menodai kedamaian malam Natal tahun 2000 ketika umat Kristen sedang merayakan ibadah Natal. Sejak itu, setiap tanggal 24 dan 25 Desember rumah-rumah gereja di kota-kota besar tak luput dari penjagaan aparat keamanan, kontras dengan kabar damai dan sukacita itu sendiri.
Kebinekaan juga terkoyak, masih ada pelarangan bagi umat Kristiani melakukan ibadah Natal, seperti terjadi di Sumatera Barat pada 2019. Sebagai negara majemuk, tentu kebhinekaan ini seharusnya dilihat sebagai energi yang konstruktif bagi percepatan kemajuan bangsa kita, bukan justru sebaliknya, energi yang destruktif.
Namun yang terjadi belakangan, kita terbiasa dengan suguhan kekerasan dan unjuk kekuatan dari kelompok-kelompok masyarakat yang memakai simbol dan slogan keagamaan. Kelompok masyarakat intoleran yang berdaster tidak hanya merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi juga merobek-robek etika dan budaya sebuah bangsa yang menganut falsafah Pancasila dab Bineka Tunggal Ika.
Saking mabuk beragama sampai-sampai pohon cemara dan palma juga menjadi “korban” dari para pemilik surga ini. Padahal sejak kapan pohon cemara dan daun palma ini punya agama? Ya, begitulah kelompok intoleran di Indonesia ini selalu berpikir terbalik karena tak punya akal sehat.
Bila politisasi agama di era Orde Baru masih terselubung, di era sesudahnya langsung terlihat. Dari konflik antarumat beragama sampai konflik politik, tampak agama mudah diperalat untuk meligitimasi kekerasan dan memberi dukungan politik. Absolutisme agama dipolitisasi.
Kecenderungan politisasi agama dalam kondisi masyarakat kita yang masih religius memungkinkan peningkatan konflik sosial bernuansa agama. Padahal, kita mesti belajar dari pengalaman negara-negara di Timur Tengah. Banyak negara yang hancur karena politik identitas. Lebanon 15 tahun perang saudara antar agama untuk berebut kekuasaan. Suriah selama 7 tahun perang karena narasi Suni vs Syiah. Afganistan dikuasai Taliban karena ingin menjadikannya negara agama.
Identitas bukan hanya agama, tapi juga suku dan ras. Rwanda tahun 1994 habis 1 juta jiwa dalam waktu 3 bulan, karena suku Hutu merasa lebih pantas berkuasa dari suku Tutsi. Bahkan di Indonesia kita mengenal konflik Sampit tahun 2001 dan konflik di Ambon, Maluku tahun 1999.
Agama pada dasarnya menentang kekerasan. Fitrah agama menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, kesucian hidup, keluhuran akhlak, ketenangan, dan kedamaian. Perusakan, penjarahan, perampasan nyawa, teror, intimidasi, kebencian, curiga, permusuhan, pengkotak-kotakan, fitnah dan menyebar kabar bohong (hoaks) serta menipulasi isu-isu yang berbungkus agama, tidak sesuai dengan jiwa agama. Manusialah yang menjerumuskan agama ke dalam praktek kekerasan.
Panggilan manusia di dunia adalah merayakan kehidupan. Dalam hal itu, tiada sekat-sekat primordial yang boleh memisahkan manusia satu sama lain. Perayaan Natal menggugah kesadaran kita untuk merayakan kehidupan dalam kasih dan solidaritas dalam persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa merdeka yang menganut falsafah Pancasila dan Bineka Tunggal Ika.