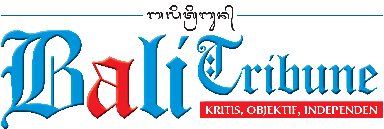Beberapa tahun belakangan ini kita terbiasa dengan suguhan kekerasan dan unjuk kekuatan dari kelompok-kelompok masyarakat yang memakai simbol dan slogan keagamaan.
Bila politisasi agama di era Orde Baru masih terselubung, di era sesudahnya langsung terlihat. Dari konflik antarumat beragama sampai konflik politik, tampak agama mudah diperalat untuk meligitimasi kekerasan dan memberi dukungan politik. Absolutisme agama dipolitisasi.
Kecenderungan politisasi agama dalam kondisi masyarakat kita yang masih religius memungkinkan peningkatan konflik sosial bernuansa agama. Padahal, kita mesti belajar dari pengalaman negara-negara di Timur Tengah. Banyak negara yang hancur karena politik identitas. Lebanon 15 tahun perang saudara antar agama untuk berebut kekuasaan. Suriah selama 7 tahun perang karena narasi Suni vs Syiah. Afganistan dikuasai Taliban karena ingin menjadikannya negara agama.
Identitas bukan hanya agama, tapi juga suku dan ras. Rwanda tahun 1994 habis 1 juta jiwa dalam waktu 3 bulan, karena suku Hutu merasa lebih pantas berkuasa dari suku Tutsi. Bahkan di Indonesia kita mengenal konflik Sampit tahun 2001 dan konflik di Ambon, Maluku tahun 1999.
Genderang kekerasan di Ambon yang pecah pada 19 Januari 1999 adalah bencana kemanusiaan yang maha dahsyat: "kerusuhan komunal" antara sejumlah kelompok Kristen dan kelompok Muslim.
Daerah yang selama ini dikenal dengan sebutan "Ambon Manise" lantaran penduduknya dikenal toleran terhadap agama dan relasi kemanusiaan, di samping keindahan alam dan lautnya, tiba-tiba berubah menjadi "Ambon Pahite" yang sangat getir.
Aksi kekerasan brutal yang merenggut ribuan jiwa dan menghancurkan semua tatanan kehidupan bermasyarakat. Setidaknya (menurut catatan MAULA—Masyarakat Plural Untuk Keadilan), hingga 2 September 1999, telah tercatat 1.132 korban tewas, 312 orang luka parah, 142 orang luka ringan. Sebanyak 765 rumah terbakar, 195 ruko serta puluhan kendaraan hancur dibakar. Di samping itu 100.000 ribu orang meninggalkan tempat tinggalnya dan sedikitnya 30.000 orang menjadi pengungsi di 60 kamp penampungan, khususnya di kota Ambon dan sekitarnya.
Sejumlah sejarawan dan ilmuwan sosial spesialis kajian Maluku seperti Gerry van Klinken, Jacques Bertrand, Chris Wilson, Dieter Bartels, Birgit Brauchler, Tony Pariela, dan lainnya menyebut, tragedi kemanusiaan di Ambon dan kawasan Maluku sebagai konflik Kristen-Muslim terbesar dan terparah dalam sejarah sosial-politik di Indonesia.
Tahu dari akar semua masalah yang berujung pada banyaknya kehilangan jiwa? Ya, politik kekuasaan. Kursi kekuasaan itu memang rasanya manis bagi sebagian orang yang punya sifat tamak. Dengan kekuasaan dia bisa mengontrol banyak hal yang pada akhirnya urusannya adalah kekayaan yang tidak bisa habis dimakan tujuh turunan. Politik, kekuasaan dan bisnis adalah lingkaran setan yang tidak akan pernah habis sampai akhir zaman.
Dan untuk membentuk kebanggaan terhadap identas, dibutuhkanlah simbol-soimbol. Simbol itu bisa berupa lambang, bisa juga berupa orang. Dan di negara berkembang yang selalu butuh sosok untuk menyelesaikan masalah besar, biasanya dibangun simbol orang yang dinarasikan sebagai pembebas, revolusioner, wakil dari umat yang tertindas.
Itulah kenapa saya setuju sekali, ketika TNI – POLRI memulai dengan menghancurkan baliho Rizieq Shihab Shihab, yang dibangun oleh pengikutnya— Front Pembela Islam (FPI), dengan dana dari elit politik hitam yang tidak berperasaan.
Yang dilakukan TNI bukan sekadar menghancurkan sebuah baliho yang harganya cuman seratus ribu perak, tapi mencegah dampak yang lebih luas dari kengerian akibat politik identitas.
Kepulangan Habib Rizieq Syihab dari Arab Saudi, Selasa (10/11/2020) lalu membawa persoalan yang begitu kompleks di tengah pandemi Covid-19. Beberapa tokoh nasional diindikasikan terlibat di belakangnya. Rizieq yang dielukan oleh pengikutnya sebagai imam besar FPI, justru memantik api perpecahan bangsa melalui ucapan-ucapan sampah yang kotor dan provokatif hingga pelecehan dan penghinaan terhadap institusi negara.
Bayangkan, ketika simbol dalam baliho itu dibiarkan, maka akan muncul perlawanan dari komunitas lain yang merasa terancam. Semisal, karena dia sering menghujat agama lain untuk membangkitkan superioritas dalam komunitasnya, maka agama lain yang mayoritas di daerah tertentu bisa bergerak dan melawan.
Dan siapa yang rugi pada akhirnya jika terjadi gesekan? Ya, masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa, yang lemah. Mereka inilah korban terbesar dalam sebuah perang. Orang yang sudah tua, wanita dan akan-anak.
Agama pada dasarnya menentang kekerasan. Fitrah agama menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, kesucian hidup, keluhuran akhlak, ketenangan, dan kedamaian. Perusakan, penjarahan, perampasan nyawa, teror, intimidasi, kebencian, fitnah dan menyebar kabar bohong (hoaks), tidak sesuai dengan jiwa agama. Manusialah yang menjerumuskan agama ke dalam praktek kekerasan.
Agama berfungsi sebagai kekuatan moral yang ampuh. Ajaran agama mendorong orang berbuat baik, menjauhkan diri dari kejahatan dan hawa nafsu, mengejar ketenteraman dan keselamatan di dunia maupun akhirat. Agama memotivasi orang untuk mengamalkan kebaikan kepada sesama dalam semangat pengabdian kepada Tuhan. Propaganda keagamaan yang bertentangan dengan kebaikan dan kesucian hidup melawan fitrah agama itu sendiri.
Sudah jelas agama dasarnya tidak menganjurkan kekerasan dan hal-hal yang bakal menyengsarakan orang lain. Namun, demi kodratnya sebagai instrumen manusia untuk berhubungan dengan kuasa-kuasa adikodrati atau Yang Mahakuasa, agama mudah melegitimasi tindak kekerasan, terutama pada awal kelahiran dan penyebaran agama. Demi tegaknya kewibawaan agama, sanksi-sanksi kaku dan keras diberlakukan guna mencapai sebuah masyarakat ideal dengan keseragaman tata hukum.
Tindak kekerasan dalam agama saat pemunculannya bersifat darurat. Peristiwa kekerasan dalam Kitab Suci tidak dimaksudkan menjadi model kehidupan umat sepanjang masa, apalagi masyarakat yang keadabannya kian berkembang. Realitas kemajuan dan kemajemukan masyarakat adalah perkembangan yang tidak boleh dibuat mundur.
Agar masyarakat tidak berjalan mundur, agama harus dihadirkan dalam bentuk beradab. Yang diamalkan dari agama adalah nilai-nilai kemanusiaanya yang menghargai toleransi (bukan radikal), yang membangun (bukan merusak), yang menghidupkan (bukan mematikan).***