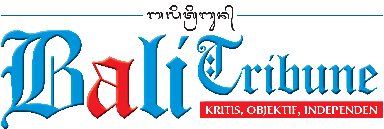BALI TRIBUNE - Masih segar dalam ingatan kita. Bencana sosial dengan gempa dan tsunami yang terjadi pada 2018 silam di sejumlah kawasan Indonesia merenggut senyum warga negeri ini. Bencana alam bertubi-tubi mengguncang, dari gempa di NTB hingga Palu-Donggala di Sulawesi Tengah. Lalu awal 2019 dibuka dengan sejumlah bencana tanah longsor dan banjir membuat Indonesia kembali berduka dengan ratusan warga yang kehilangan nyawa, rusaknya tempat tinggal, dan hilangnya sanak-saudara. Tak hanya itu. Bencana sosial terus menghajar warga negeri ini, dengan perdebatan tanpa henti, beserta hasutan dan kebencian yang membakar nyali. Walaupun kita hidup di negeri yang dianugerahi kesuburan tanah, namun diintai oleh bencana-bencana dari siklus bumi, di kawasan ring of fire. Negeri Zamrud Katulistiwa ini diguyur kenikmatan sebagai bangsa kreatif dengan semangat gotong royong, namun dipecah belah oleh hoaks dan api kebencian yang disulut di media sosial, terlebih pada momentum kontestasi politik 2019 ini. Bencana alam membuat warga negeri ini menangis, tapi alam memiliki siklusnya. Pelajaran penting untuk mengais jejak pengetahuan dari tanda-tanda dan ilmu titen nenek moyang kita. Warga Indonesia seolah terputus dari sejarah pengetahuan dan kearifan kebudayaannya. Cara kita menghargai alam, tergeser oleh kerakusan mengeksploitasi, sembari kita seolah melupakan penghormatan sekaligus kecintaan merawat alam dan merawat negeri ini. Di sisi lain, gempa sosial yang merembet dari perdebatan di media sosial hingga interaksi antar-personal dalam kehidupan nyata, menggeser nilai-nilai kearifan kita. Dalam kerumunan perdebatan, yang muncul hanyalah narasi kebencian dan saling menyalahkan. Kita berdebat tanpa ujung, dari satu isu ke isu lain dengan napas tersengal-sengal. Seolah, kita telah kehabisan oksigen pengetahuan dan kesabaran merenungi kehidupan. Inikah wajah Indonesia kita? Krisis toleransi Bencana di ruang interaksi sosial kita diperparah dengan tumbuh suburnya kebencian dan intoleransi. Laporan Setara Institute menyebutkan, intoleransi semakin berdenyut di nadi keindonesiaan kita. Sepanjang 2017, terjadi 155 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di 29 provinsi di Indonesia. Sementara, pada awal 2018 lalu, narasi intolerasi memenuhi wajah keindonesiaan kita. Kita masih belum lupa tentang kasus pembubaran kegiatan bakti sosial Gereja Katholik St Paulus Pringplayan, Bantul, Yogyakarta. Lalu, tragedi penyerangan di Gereja Katolik St Lidwina, Trihanggo Sleman, dan pengusiran seorang biksu di Tangerang, Banten. Paparan riset Setara Institute juga melengkapi riset sebelumnya, yang meringkas bahaya intoleransi di ranah pendidikan. Dari survei di 171 sekolah, terungkap betapa siswa SMA rentan terpapar radikalisme dan gejala terorisme. Dari analisa 18 pertanyaan kunci, terungkap sebesar 2,4 persen siswa memiliki sikap intoleransi aktif. Sedangkan, siswa yang terpapar radikalisme sebanyak 0,3 persen. Jumlah ini termasuk menghawatirkan, karena bibit intoleransi telah tersemai di level siswa. Tunas-tunas muda di ruang pendidikan kita perlu diselamatkan dengan oksigen kasih sayang dan cinta kemanusiaan, bukan kebencian dan hasutan kekerasan. Sementara, guru-guru yang seharusnya mendidik dan memberi keteladanan, juga terinfeksi virus kebencian. Alarm bahaya ini terdengar dari survei PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang dirilis pada Oktober 2018. Survei tersebut dilakukan pada 6 Agustus 2018 hingga 6 September 2018, dengan menggunakan unit analisis guru Muslim dari level TK/RA sampai SMA/MA untuk semua mata pelajaran. Dari survei ini, variabel utama yang ingin digali yakni level intoleransi dan radikalisme guru, serta faktor-faktor dominan yang mempengaruhi. Sampel guru yang paling banyak diambil sejumlah 2.237 dengan margin of error 2,07 persen serta tingkat kepercayaan 95 persen. Dari laporan survei ini, terungkap betapa level intoleransi guru di beberapa kawasan di Indonesia cukup tinggi, serta mengarah bahaya pada rusaknya ekosistem pendidikan di negeri ini. Persentasenya secara umum di atas 50 persen untuk guru dengan opini intoleran, dengan 46,09 persen di antaranya mempunyai pandangan radikal. Pada sisi intensi-aksi, levelnya cukup mengkhawatirkan untuk masa depan pembelajaran di negeri ini. Terungkap data, 37,77 persen guru intoleran serta 41,26 persen radikal. Menurut PPIM, ada tiga faktor penting yang menjadi fondasi tumbuh suburnya intoleransi di kalangan guru. Yakni, Pandangan Islamis Riset ini mengungkap sejumlah 40,36 persen guru setuju bahwa seluruh ilmu pengetahuan sudah ada di Al Quran, dengan demikian tidak perlu mempelajari khazanah pengetahuan dari Barat. Faktor demografi Jenis kelamin, sekolah madrasah versus sekolah negeri, status kepegawaian, penghasilan dan usia. Kedekatan dengan ormas dan sumber pengetahuan Islam. Guru-guru yang memiliki kedekatan dengan ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, memiliki pandangan yang lebih toleran dan moderat. Dari survei ini, tergambar bagaimana pandangan guru-guru terhadap indoktrinasi agama serta isu relasi sosial antar-agama. Sebanyak 56 persen guru tidak setuju jika non-Muslim boleh mendirikan sekolah berbasis agama di sekitar mereka. Kemudian, 21 persen guru tidak setuju jika ada tetangga yang berbeda keyakinan mengadakan acara keagamaan di lingkungan mereka. Ironisnya, sejumlah 33 persen guru setuju menganjurkan orang lain berperang demi mewujudkan negara Islam. Lalu, 29 pendidik setuju untuk ikut berjihad di Filiphina Selatan, Suriah, dan Irak, untuk tujuan negara Islam. Dapat dicatat bahwa laporan survei menjadi lonceng bahaya bagi masa depan pendidikan dan narasi keindonesiaan kita. Fakta yang ada menunjukkan, banyak guru di negeri ini belum mencerminkan diri sebagai pendidik ideal dan inovatif yang siap mendidik siswa dengan profesionalisme dan optimisme. Kapasitas intelektual yang rendah, kedisiplinan yang lemah, semangat belajar yang hampir hilang, integritas moral yang sering menyeleweng, dan dedikasi sosial yang rendah adalah bagian potret buram guru di negeri ini. Hal ini membuat lembaga pendidikan berjalan stagnan, bahkan terkesan mundur. Bahkan, yang lebih menyedihkan lagi, guru-pendidik yang seharusnya menebar keteladanan dan nilai-nilai toleransi, malah menanam benih kebencian. Perlu ada langkah taktis-sistematis untuk menghadirkan solusi atas bencana intoleransi dari ranah pendidikan, dari jantung ke-Indonesia-an kita. Menghadirkan pendidikan yang menebarkan cinta kasih dan program-program silaturahim gagasan sekaligus saling mengenal antar-komunitas lintas agama-budaya, menjadi mutlak diperlukan. Api kebencian dari dunia pendidikan harus dipadamkan dan disiram dengan nilai-nilai cinta kasih serta kepedulian pada sesama. Indonesia membutuhkan pendidik yang menawarkan sejuknya toleransi dan perdamaian, bukan mengobarkan kebencian.