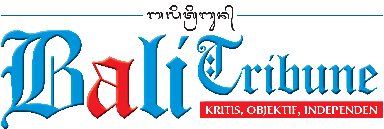BALI TRIBUNE - MPR RI melalui Ketua Badan Sosialisasi Ahmad Basarah menengarai, saat ini ada upaya adu domba pertentangkan agama dan negara. (BALI TRIBUNE, 24/3. Hal.3). Tengara itu jelas nyata, bukan manipulatif. Hanya perlu didalami mengapa hal itu baru menguat saat ini. Analisis sementara menunjukkan, Jokowi-JK sedang melakukan revolusi mental ideologi bangsa untuk segera mengantarkan Indonesia kepada negara modern yang egaliter dan rasional, namun masih berkontraksi dengan hambatan sosiologis yang belum ditemukan terapi yang pas.
Seperti biasa, yang namanya revolusi selalu ada efek kejut atau dalam bahasa futorolog Alvin Toffler (1928), disebut cultur shock. Tentu saja yang mesti dikoreksi adalah prosesnya, bukan tujuannya karena tujuannya sudah baik. Bahwa mengelola negeri pluralisme Indonesia mesti berbasis kepada keadilan proporsional. Artinya, negara wajib adil dalam memberi akses warga yang pluralis namun tetap dengan kaidah keadilan proporsional.
Ada hal lain yang perlu menjadi bahan refleksi. Bahwa selama ini tuntutan perbaikan kinerja selalu ditujukan kepada Pemimpin. Padahal, perubahan dalam sebuah organisasi, apalagi organisasi negara, dimungkinkan jika follower (rakyat) juga meski memberi kontribusi. Kontribusi kepada Pemerintah dalam menata bangsa agar Negara dan Agama tidak diposisikan secara subordinatif atau kontradiktif.
Harusnya, usia kemerdekaan RI yang sudah mencapai 72 tahun, masalah hubungan Negara-Agama mesti sudah selesai. Sebab, sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa sudah terlibat amat serius mendiskusikan hal itu, termasuk menemukan format idiologis dan bentuk negara yang pas sehingga kita boleh bersatu dalam perbedaan sejak saat itu.
Memang harus diakui, negara kebangsaan Indonesia memang unik. Dia terbentuk dari keping-keping perbedaan di hampir semua segi. Berbeda dengan Jerman, Inggris, Prancis, Italia, Yunani, yang menjadi negara bangsa karena kesamaan bahasa. Atau Australia, India, Sri Lanka, Singapura, yang menjadi satu bangsa karena kesamaan daratan. Atau Jepang, Korea, dan negara-negara Timur Tengah, yang menjadi satu karena kesamaan ras.
Indonesia, sebagaimana ditulis Siswono Yudohuso (KOMPAS, 2/6/2005), menjadi satu negara bangsa meskipun terdiri atas banyak bahasa, etnis, ras dan terserak di puluhan ribu pulau. Hal ini terwujud karena kesamaan sejarah masa lalu; memiliki kesamaan wilayah selama 500 tahun Kerajaan Sriwijaya, 300 tahun kerajaan Majapahit, dijajah Belanda selama 350 tahun dan diduduki Jepang 3,5 tahun.
Dengan demikian, debat tentang pluralisme Indonesia, hubungan negara dengan agama, dan ideology penyatu bangsa harusnya sudah selesai. Tinggal bagaimana Pemerintah sebagai pengelola negara yang mendapat mandat rakyat, mesti memiliki kemampuan yang memadai untuk menata negeri pluralis ini. Tentang ideologi Pancasila misalnya, setelah disepakati dan diputuskan melalui rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945, ada begitu banyak ujian yang dialami baik secara fisik maupun konsep, namun semua itu akhirnya selesai juga dan kita kembali kepada komitmen awal, Pancasila.
Demikian juga hubungan Negara-Agama seharusnya sudah selesai. Bahwa Negara-Agama dalam negeri Pancasila terjalin berkelindan erat sejak negara ini berdiri. Lihatlah faktanya; Negara ikut mengatur dan memberi kontribusi pada pendirian rumah ibadah semua agama, terlibat dalam dan memfasilitasi hajat-hajat agama seperti MTQ, Pesparawi, kegiatan-kegiatan keagamaan Hindu, Budha dan Konfutzu.
Mengurus perjalanan haji, zakat, ekonomi syariah dalam Islam dan berkontribusi kepada kegiatan ibadah semacam untuk agama lainnya. Singkatnya; hadirnya kementerian agama yang memperoleh jatah APBN nomor tiga terbesar, sudah menunjukan bahwa Agama-Negara tetap berada dalam pola hubungan yang harmonis. Hal yang tidak boleh ada yakni bahwa Negara ditundukkan untuk kepentingan agama tertentu.
Dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan misalnya; ada kontribusi seluruh umat beragama di sana, meski tentu saja secara proporsional. Umat Islam yang memiliki massa terbanyak dan menjadi penikmat terbesar dalam bernegara, memang memberi kontribusi lebih besar dalam perjuangan itu. Namun, secara kualitas, keikutsertaan seluruh umat beragama dalam memerdekakan bangsa, sudah tercermin secara jelas dalam album sejarah.
Jenderal Sudirman, meski cengkeraman tuberclase akut, masih mampu memimpin perang gerilya dengan mengandalkan spirit ilahiah. Sholat 5 waktu, zikir dan memuji Tuhan, tetap melekat pada bibirnya meski sampai musur tertundukkan. Brigjend DI Pandjaitan yang menjadi penantang keinginan kaum komunis untuk bertahta di negeri Pancasila, harus berkorban nyawa. Bahkan, seperti direkam sejarah 31 September 1965, hujan peluru menerjang tubuhnya, saat sang Jenderal masih melantunkan doa-doa sesuai ajaran Kristiani.
Demikian pula spirit Hindu yang masih bertaut erat dengan budaya Jawa-Bali ketika itu, dijadikan sebagai pelecut nyali para pejuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spirit Hindu yang tertuang dalam epos Ramayana dan Mahabrata antara lain menjadi spirit bagi Suwardi Suryaningrat untuk mendirikan Taman Siswa. Demikian juga Sutomo, yang ketika bergelut dengan konsep hubungan Negara-Rakyat mengajukan sebuah prinsip yang sangat terkenal; “Bekerja dengan tidak mengenal buah”.
Kata Sutomo, jangan sistem yang ditundukkan untuk mengakomodasi kemauan segelincir rakyat, tetapi rakyat yang diubah untuk disesuaikan dengan sistem. Hal ini sejalan dengan isi sloka Bagawadgita berintikan spirit pengabdian; kewajiban harus dilaksanakan dengan semangat pengabdian kepada Tuhan. Laksanakan Karmamu dan persembahkan kepada Tuhan, selain bekerja tanpa pamrih. Selain perjuangan fisik yang dikobarkan I Gusti Ngurah Rai dan prajurit Bali lainnya, spirit Hinduis itu turut berkontribusi dalam menata mental pejuang.
Spirit Buddhis juga turut mengilhami RS Kartini ketika menggagas pemikiran tentang emansipasi. Dalam bukunya Door Duisternis tot Licht” (Habis Gelap Terbitlah Terang), Kartini mengaku terilhami buku karya Harold Fielding berjudul “De Ziel van een Volk” (Jiwa Suatu Bangsa) yang diterjemahkan oleh Felix Orrt ke dalam bahasa Inggris sebagai kental dengan nilai-nilai buddhis. Gagasan emansipasi Kartini kemudian menjadi modal bangsa dalam membangun kesetaraan.
Inilah bukti historis hubungan Negara-Agama tercipta dan menjadi komponen-komponen halus dalam membentuk negara Pancasila. Namun, harus diakui, debat kusir, caci maki, saling menjatuhkan antara kelompok, penganut agama dan suku, begitu masif di medsos saat ini. Pemerindah mengandalkan penegakkan hukum, namun belum terlalu efektif. Tampaknya kita masih membutuhkan terapi yang pas untuk menata negeri pluralis ini.
Pemikiran kritis Talcott Parsons berikut ini layak diadobsi. Sosiolog Kelahiran Colorado 1902 yang sempat menjadi dosen Sosiologi di Harvard University tahun 1927 ini, memberi resep agar negara bangsa tetap eksis dan lestari. Melalui bukunya Social System, dikatakan ada 4 paradigma fungsi (function paradigm) yang harus terus menerus dilaksanakan;
Kesatu; pattern maintenance, kemampuan memelihara sistem nilai budaya yang dianut, karena budaya adalah endapan perilaku manusia. Budaya itu akan berubah karena transformasi nilai dari masyarakat terdahulu ke masyarakat kini, tetapi dengan tetap memelihara nilai-nilai yang dianggap luhur. Tanpa itu, akan terbentuk masyarakat baru yang lain.
Kedua; kemampuan masyarakat beradaptasi dengan dunia yang berubah cepat. Sejarah membuktikan banyak peradaban masyarakat hilang karena tak mampu beradaptasi dengan perubahan dunia. Masyarakat yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan serta mampu memanfaatkan peluang yang timbul, akan unggul.
Ketiga; adaya fungsi integrasi unsur-unsur masyarakat yang beraneka ragam secara terus menerus sehingga terbentuk kekuatan sentripetal, yang semakin menyatukan masyarakat tersebut. Keempat; masyarakat perlu memiliki goal attainment atau tujuan bersama, yang dari masa ke masa bertransformasi karena terus menerus diperbaiki oleh masyarakat dan para Pemimpinnya.
Bila negara kebangsaan Indonesia terbentuk oleh kesamaan sejarah, maka menurut tokoh nasionalis Siswono Yudohusodo, ke depan perlu dimantapkan oleh kesamaan cita-cita , pandangan, harapan dan tujuan tentang masa depan. Pemerintah dan Rakyat Indonesia mesti mengakui bahwa ada yang salah sehingga konflik horizontal berbasis identitas (SARA) kian massif saat ini, sebagaimana terekam dalam medsos maupun sikap dan pernyataan.
Dalam konteks ini, yang perlu melakukan pembenahan bukan hanya Pemerintah, tetapi juga rakyat. Kini saatnya, rakyat harus menjadi follower yang baik untuk menyongsong Indonesia baru yang egaliter, rasional serta adil dan makmur.