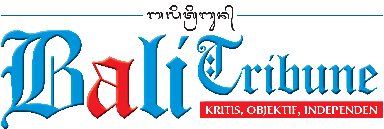Oleh: Wayan Windia - Guru Besar di Fak. Pertanian Unud, dan Ketua Stispol Wira Bhakti.
balitribune.co.id | Pada bulan Februari yang lalu, saya menulis opini (di Harian Bali Tribune) tentang konflik sosial yang terjadi, berbasis kawasan Pura Marceti. Kemudian, beberapa hari yang lalu saya mendapat kiriman berita media-online, yang memuat keterangan Bendesa Adat Medahan. Lho, ada apa ini? Ternyata bendesa membantah uraian opini saya. Bahwa dalam dunia pers, bantah-membantah adalah hal yang biasa. Itu adalah bagian dari hak jawab seseorang, sesuai kode etik jurnalistik.
Tetapi membuat kesimpulaan dan pernyataan yang menyatakan seseorang melakukan perbuatan tertentu, misalnya : “pembohongan publik”, sebaiknya dilakukan dengan hati-hati, dan melakukan chek-rechek yang seksama. Sebaiknya, jangan secara sembarangan.
Sejatinya, kalau betul opini yang saya buat, telah dibaca dengan cermat dan hati-hati, maka pernyataan bendesa seperti itu, tidak akan muncul. Bahwa apa yang saya tulis itu, adalah berdasarkan pernyataan dari tiga desa adat lainnya. Itu adalah kesimpulan rapat dari ketiga bendesa adat tersebut, pada tanggal 31 Januari 2022. Saya hanya mengutip saja. Bahkan itulah yang menjadi lead tulisan saya. Jadi, siapa sebetulnya yang melakukan “pembohongan”? Saya atau bendesa adat Medahan. Silahkan pembaca yang menilai.
Tentang pertanyaannya sekitar pemahaman saya tentang Pura Masceti, saya langsung saja jawab : sangat paham. Karena saya membaca buku tentang Pura Masceti. Dikatakan bahwa berdasarkan Dewa Purana Bangsul, Pura Masceti dibangun bersamaan dengan salah satu pura lainnya, yakni Pura Er Jeruk di Sukawati. Pura Er Jeruk adalah juga pura yang dikelola subak di kawasan Subak Gde Sukawati. Bahwa Pura Masceti mulai dibangun sejak kedatangan Rsi Markandya, dengan bangunan yang sederhana. Kemudian diperluas lagi pada saat kedatangan Mpu Kuturan di Bali. Bahkan ada indikasi bahwa pura ini sudah eksis sejak zaman pra-Hindu.
Disebutkan bahwa Pura Masceti dikategorikan dalam kelompok pura fungsional (swagina). Meski sebagai pura swagina, tetapi memang pura itu dalam status pura kahyangan jagat. Dalam hal ini tidak hanya jagat Desa Adat Medahan, tetapi juga jagat Gianyar, dan juga jagat Bali. Bahwa pangemong Pura Masceti adalah seluruh warga Subak (Gde) Pakerisan Teben dan Subak (Gde) Gunung Sari. Terdiri dari 20 subak. Yakni : Subak Gaga, Subak Dayang, Subak Diga, Subak Dewa, Subak Amping, Subak Poh Gading, Subak Betuas, Subak Slukat, Subak Sengauk, Subak Abang, Subak Dukuh, Subak Tedung, Subak Nengan, Subak Abu, Subak Celuk, Subak Ceti, Subak Padang Legi, Subak Panjan, Subak Jurit, dan Subak Peling.
Organisasi subak-subak inilah yang mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan Pura Masceti, atau sebagai pengemong Pura Masceti. Sedangkan warga Desa Medahan-Keramas yang tidak memiliki tanah sawah dan tidak berstatus sebagai anggota subak, hanya berstatus sebagai penyungsung. Sehingga bebas dari kewajiban membiayai dalam bentuk biaya pemeliharaan dan upacara piodalan.
Disebutkan pula bahwa Pura Masceti adalah merupakan Parhyangan subak, persawahan adalah merupakan Palemahan subak, dan anggota subak adalah merupakan Pawongan subak. Bahwa Pura Masceti diberikan status sebagai Pura Subak. Hal ini sesuai dengan Perda No. 9 tahun 2012 tentang Subak. Jadi, Perda tentang subak terbit jauh lebih awal dibandingkan dengan Perda tentang Desa Adat. Bahkan pernah ada wacana untuk menjadikan Pura Masceti sebagai pura untuk semua subak di Kab. Gianyar. Hal ini wajar, karena pada saat-saat itu subak di Bali diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia.
Bagaimana dengan pernyataan bendesa bahwa yang bersangkutan melakukaan penataan sesuai Perda No. 4 tahun 2019 ? Lalu pertanyaannya, pasal yang mana yang diterapkan? Kalau melakukan penataan seharusnya dilakukan di palemahan desa adat. Dalam Pasal 10 Perda tersebut, yakni pada Ayat (2) disebutkan bahwa palemahan desa adat adalah meliputi tanah milik desa adat, dan tanah guna kaya. Pertanyaan lanjutan, apakah tanah di kawasan Pura Masceti adalah tanah milik desa adat, sesuai Pasal 10 tersebut?
Berkait dengan hal-hal tersebut, maka sudah sejak awal saya sarankan agar semua pihak agar bisa duduk bersama. Apalagi kasusnya berkait dengan pura. Katanya ada wacana, bahwa kita di Bali memiliki filsafat paras-paros, tatwan asi, tri hita karana, dan lain-lain. Filsafat kuno itu, jangan hanya menjadi hiasan bibir. Harus di-implemantasi-kan. Bila secara empirik pihak subak mampu mengelola kawasan pura dengan baik, kenapa tidak dilanjutkan saja, sesuai tradisi (kune dreste) ? Jangan diintervensi.
Karena subak adalah lembaga yang otonum, yang batas-batasnya berbasis hidrologis. Ia memiliki juga parhyangan, pawongan dan palemahan. Sedangkan desa adat, batasnya berbasis administratif. Ia juga memiliki parhyangan, pawongan, dan palemahan. Semuanya harus bisa berkoordinasi. Inilah yang disebut dalam ilmu sosiologi sebagai konsep polisentri. Leluhur kita di Bali telah mengembangkan konsep polisentri dalam realitas sosialnya. Leluhur kita dahulu tidak ada yang tamatan SLTA (red : karena dulu tidak ada sekolah formal), kok beliau bisa bekerja dengan paras-paros. Barangkali kita harus lebih banyak merenung dan belajar dari kebajikan serta kebijakan Raja Udayana, Raja Marakata, dan Mpu Kuturan.