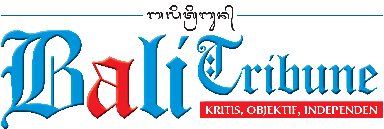Oleh : Putu Suasta
balitribune.co.id - Cebong dan kampret mulai menunjukkan tanda-tanda “kematian” sejak Prabowo bertemu dengan Jokowi yang diikuti dengan upaya-upaya rekonsiliasi oleh berbagai elit politik. Ruang-ruang publik tidak lagi dibisingkan oleh perseteruan antara cebong dan kampret. Masyarakat tak lagi terbelah ke dalam dua kubu karena perbedaan pilihan politik. Ini tentu kabar baik. Kabar buruknya, keterbelahan masyarakat ke dalam lebih banyak kubu mulai kelihatan dan ruang publik mulai diisi dengan kebisingan lain.
Razia buku-buku beraliran kiri (PKI) oleh sekelompok masyarakat baru-baru ini memunculkan kembali isu lawas “bahaya laten PKI”. Tudingan-tudingan sebagai “antek PKI” kemudian menyeruak dari kelompok yang berbeda pandangan dengan mereka. Maka muncul lagi indetifikasi lama antara “kita” dan “mereka”, yakni “PKI” dan “Non-PKI”. Demikian juga dengan sentimen anti investasi, impor dan segala hal yang berbau kerjasama dengan Tiongkok (Cina). Sejalan dengan itu, semakin menguat penegasan antara “yang paling Islami” dan “tidak/kurang islami” yang dibakar dengan isu pemakaian jilbab, pembenaran terhadap poligami, penyebaran gambar spanduk yang berisi penolakan terhadap pendirian tempat ibadat agama tertentu, penutupan warung yang menjual makanan non halal dan berbagai topik lain yang memicu perdebatan sengit di tengah masyarakat terutama di kanal-kanal komunikasi digital.
Demi Daya Tawar Politik Transaksional
Kemunculan kembali isu-isu lawas di atas tentu tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan pergeseran objek pertarungan di tingkat elit. Telah banyak kajian dalam ilmu-ilmu Sosial-Politik yang menunjukkan bahwa keterbelahan masyarakat merupakan representasi dari pertarungan di tingkat elit. Akan sangat sulit memungkiri keterlibatan aktor politik dalam berbagai keriuhan perdebatan atau kebisingan masyarakat. Bahkan dalam aksi-aksi kekerasan massa seringkali ditemukan jejak “invisible hand” para elit sebagaimana ditunjukkan Johan Galtung. Dengan kerangka ini kita dapat membedah mengapa demokrasi kita lebih banyak diisi dengan kebisingan publik dalam pertarungan politik identitas daripada pertarungan gagasan yang produktif.
Sebelumnya para elit bertarung untuk memperebutkan kekuasaan makro (kursi presiden dan dominasi di parlemen). Maka mobilisasi massa hanya terarah pada dua kutub: kutub Jokowi yang dilabeli sebagai cebong dan kutub Prabowo sebagai kampret. Sekarang, pertarungan di tingkat elit telah bergeser ke objek lebih kecil: perebutan kursi menteri dan sejumlah posisi-posisi penting di pemerintahan. Dalam pertarungan ini koalisi antar elit yang dibangun sebelumnya tidak berlaku lagi. Masing-masing berjuang sendiri untuk mendapatkan kursi, baik pihak yang menang maupun pihak yang kalah. Semua ingin mendapatkan pembagian “kue kekuasaan”.
Dapat dipahami jika ada banyak pihak yang memiliki kepentingan untuk memelihara kebisingan, keributan dan “kenyinyiran” di tengah masyarakat. Mereka yang memiliki akses kepada operator-operator propoganda massa akan memiliki “daya tawar” di hadapan presiden terpilih. Dengan demikian, mereka menjaga asa untuk mendapatkan mandat menghentikan atau meredakan keributan di tengah masyarakat dengan imbalan kursi atau konsesi kekuasaan.
Janji Independensi Presiden Terpilih
Salah satu keprihatinan terbesar terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia adalah tidak kunjung lahirnya sistem oposisi yang terlembaga. Pertarungan gagasan, program dan visi misi antar partai politik hanya terjadi di saat Pemilu. Setelah itu semua berlomba merapat ke pemengang tanpa peduli perbedaan gagasan, program, visi-misi demi mendapatkan bagian dari “kue kekuasaan”. Mereka yang kurang beruntung (tidak mendapatkan bagian) kemudian memposisikan diri seolah-olah oposisi (pseudo-oposisi). Istilah peseudo saya gunakan untuk menekankan bahwa mereka yang tidak berada dalam kekuasaan tidak pernah serius menjalankan fungsi oposisi yang mengawal, mengkritisi secara substantif dan menawarkan alternatif lebih baik terhadap program-program pemerintah (pemenang). Mereka hanya sibuk memunculkan isu, wacana dan bahan perdebatan baru dengan harapan memicu kebisingan di tengah masyarakat. Para pseudo opisisi hanya sibuk memobilisasi “kenyinyiran” publik terhadap pemerintah sambil menunggu kesempatan untuk diajak bergabung dalam pemerintahan dan mendapatkan “kue kekuasaan”.
Dengan kondisi di atas, seorang Presiden akan lebih banyak disibukkan dengan urusan tawar menawar baik dengan koalisinya sendiri maupun dengan koalisi yang sebelumnya merupakan lawan. Sekalipun Jokowi dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa dalam 5 tahun ke depan dirinya akan memimpin tanpa beban (karena tak memiliki agenda politik lagi untuk 2024) kita sebaiknya menahan diri untuk tidak berharap terlalu banyak terhadap terciptanya formasi di pemerintahan yang independen dan profesional. Dalam menyusun formasi para pembantunya Jokowi mustahil bisa menghindar dari tuntutan untuk “menyenangkan kawan” dan “tidak membuat lawan marah”. Kawan dan lawannya sekarang sama-sama mengincar jabatan.
Kendati demikian, kita masih layak berharap Jokowi tidak menjadikan seluruh posisi di pemerintahan sebagai bagian dari transaksi politik. Sekurang-kurangnya ada 5 posisi penting yang dinilai publik mesti diisi oleh figur-figur non partisan (terutama bukan dari partai politik atau memiliki afiliasi politik) tetapi figur-figur yang relatif indenpenden dan profesional, yakni Ketua Mahkamah Agung, Kejagung, Kapolri, Kepala BIN dan Ketua BPK.
Kelima posisi tersebut mendapat sorotan tinggi dari publik karena merupakan kunci apakah Jokowi akan mampu membangun institusi ekonomi-politik yang inklusif. Meminjam teori elit dari Francis Fukuyama, menempatkan figur-figur profesional dan independen dalam posisi-posisi tersebut merupakan syarat minimal untuk bisa membatasi perselingkungan para elit. Dalam “The End of History and the Last Man dan The Origins of Political Order”, Fukuyama menulis: “the rulling class atau kaum elit penguasa akan sibuk berselingkuh dan selalu mencari cara untuk mengendalikan pemerintahan dan mengesampingkan kemajuan sosial orang banyak demi keserakahan mereka sendiri. Suatu kinerja yg seringkali menurun akibat ulahnya. Orang-orang semacam itu harus dibatasi langkahnya dengan aturan kekuasan dalam demokrasi yang efektif, atau bangsamu akan gagal”.
Kita ingat awal periode pertama pemerintahan Jokowi mendapat sorotan tajam dari media-media besar karena menempatkan kader partai Nasdem untuk mengisi posisi Kejagung. Keputusan tersebut serta merta memunculkan pesimisme terhadap penegakan hukum di era Jokowi dan terbukti bidang itu menjadi salah satu rapor merah Jokowi dalam kurang lebih 5 tahun pemerintahannya.
Publik mesti mengawal dengan ketat agar lembaga-lembaga penegakan hukum, lembaga audit (BPK) dan BIN tidak menjadi alat politik yang dapat menciptakan chaos dan menjadikan seluruh sendi pemerintahan arena pemuas nafsu kekuasaan para elit. Semoga Jokowi benar-benar menyadari bahaya ini.(u)