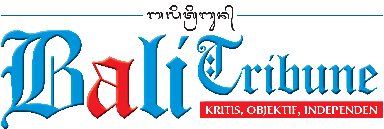balitribune.co.id | Di hari minggu, biasanya televisi menampilkan acara yang sendu. Mungkin untuk mengendurkan pikiran yang tegang, di hari-hari sebelumnya. Berbeda dengan hari minggu kemarin. Liputan televisi sangat hiruk pikuk, dan menegangkan. Ada kecelakaan pesawat Sriwijaya Air di Kepulauan Seribu. Banyak orang yang tertegun. Karena pesawat hanya sempat terbang selama empat menit, dan kemudian terjatuh di laut dalam.
Memang, masa kritis penerbangan pesawat adalah saat 10 menit setelah lepas landas, dan 10 menit sebelum mendarat. Tetapi siapa sangka pesawat hanya terbang hanya empat menit? Saya terbayang, para penumpang masih mengenakan sabuk pengaman. Dan pandangan mata masih melihat-lihat pramugari yang sibuk, untuk menyiapkan kudapan atau makan siang.
Tetapi di hari Sabtu sore (9/1) itu, Takdir berkata lain. Pesawat Sriwjaya Air kabarnya berbelok, menuju ke arah jalur yang menyimpang, dan kemudian terjatuh. Kalau nanti kotak-hitam pesawat ditemukan, kita pasti akan mendengar di sana, lengkingan jerit tangis yang memilukan. Jerit-tangis, adalah usaha manusia untuk menghilangkan stress yang datang mendadak. Tetapi selanjutnya kita harus berserah kepada Takdir, kepada Sang Maha Pencipta, kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa.
Biasanya orang Barat menyebutkan slogan hate Monday. Kebencian di hari Senen, karena terlanjur sangat menikmati liburan di hari Sabtu dan Minggu. Tetapi kali ini kita di Indonesia, mesti harus mengatakan hate Sunday. Sebuah kebencian di hari Minggu, karena sehari sebelumnya ada musibah yang sangat mencekam.
Pada hari yang nyaris sama, ada longsor di Sumedang. Menyebabkan 16 orang meninggal, delapan orang luka-luka, dan banyak rumah yang hancur. Untuk hal itu, saya masih bisa men-justifikasi. Mungkin karena penduduk di sana sangat serakah. Membabat hutan seenaknya, membuang sampah di sungai, dan tidak hirau pada lingkungan alam. Kemudian mereka mendapat pahala dari karma yang diperbuat. Ya, demikianlah adanya, kalau kita percaya pada hukum karma-pahala.
Tetapi, bagaimana dengan kecelakaan sebuah pesawat terbang? Pesawat dibuat dengan perhitungan matematik yang matang. Di uji berkali-kali. Sebelum terbang, di test dengan teliti. Penumpangnya membayar sangat mahal. Menunggu penerbangan, bahkan dalam waktu berjam-jam. Kalau penerbangan ditunda karena berbagai alasan, maka para penumpang umumnya pasrah saja. Kalau semua kondisi dicatat sudah aman, barulah penerbangan di lakukan.
Plus, pilot pesawat Sriwijaya itu adalah mantan perwira TNI-AU, yang sudah malang-melintang di udara selama sekitar 35 tahun. Saya adalah orang yang sangat membanggakan komunitas TNI. Pastilah sebagai mantan warga TNI, pilot itu sangat disiplin dan penuh kewaspadaan. Lalu terbiasa harus cepat mengambil keputusan yang tepat. Pertanyannya, kenapa masih bisa sampai terjadi bencana kecelakaan yang sangat menyedihkan itu?
Kontemplasi ini sangat mengganggu pikiran saya. Lalu mendorong saya ke meja kerja, dan membuka laptop. Saya teringat pada buku bacaan Kitab Mahabrata. Bahwa semua kejadian adalah karena kehendak Takdir. Apapun yang “terjadi” dan “tidak terjadi”, adalah karena kehendak Tuhan YME. Tidak ada yang bisa melawan Takdir. Manusia bisa “menaklukkan” bulan, tetapi manusia tidak bisa melawan Takdir.
Gugurnya Begawan Bisma, Guru Drona, Karna, Gatotkaca, Bimaniyu, dan bahkan Duryudana serta Dursasana, adalah karena Takdir. Selanjutnya Takdir juga menghendaki tetap hidupnya Sang Panca Pandawa dalam Perang Berata Yudha yang sangat heroik. Gugurnya Sang Gatotkaca di tangan Karna (Raja Angga), adalah Takdir untuk menyelamatkan Pangeran Arjuna. Tampaknya, kemunculan Takdir, karena adanya berbagai Sumpah para satrya sejati. Semua sumpah-sumpah para satrya itu dikelola oleh Kresna, yang dipercaya sebagai titisan Dewa Wisnu. Sri Kresna-lah yang menentukan siapa yang harus gugur dalam perang besar itu.
Ah, rasanya, kita terlalu mengenang masa lalu (atita). Tetapi jelaslah, bahwa masa depan (anagata) dari semua yang ditinggalkan oleh korban Sriwijaya Air, adalah juga ditentukan oleh Takdir. Ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ditentukan oleh Karma, yang kita perbuat di masa lalu, dan di masa kini (wartamana).
Di televisi, saya menyaksikan seorang lelaki setengah baya menangis tersedu-sedu, ketika diwawancarai oleh pers. Orang itu terlihat sudah menghindar, tetapi pers tampaknya masih mengejar. Hal ini tidak dibenarkan oleh Kode Etik Jurnalistik. Seseorang (korban) memiliki hak privasi. Hak itu harus dihormati oleh pers. Jangan mengganggu seseorang yang menjadi korban.
Orang itu mengaku sudah menunggu istri dan tiga orang anaknya, selama berjam-jam di Bandara Supadio, Pontianak. Istrinya sempat melakukan video call, bahwa pesawat Sriwijaya delay selama satu jam. Semua, ketiga anaknya itu masih di bawah umur. Anaknya yang tertua, umurnya empat tahun. Anaknya yang kedua, masih dua tahun, dan yang ketiga, justru masih bayi (enam bulan). Mereka ingin menengok suamiya, yang bekerja di Pontianak. Tetapi akahirnya mereka tidak akan pernah bertemu di alam fana untuk selama-lamanya. Sungguh suatu peristiwa yang tragis.
Ada juga pasangan suami-istri yang baru menikah, dan akan mengadakan pesta keluarga di Pontianak. Lalu Takdir menentukan lain. Saya tak bisa merasakan, betapa pedihnya hati orang-orang, yang sedang mempersiapkan pesta meriah sebuah pernikahan. Meski di masa pandemi sekalipun. Waduh, tatkala saya sedang mengetik naskah ini, saya menerima kiriman puisi, karya WS Rendra. Ia bercerita tentang detik-detik terakhir kehidupannya. Bahwa hidup ini adalah titipan Tuhan, dan kita harus hidup dalam rendah hati. Memangnya, apa yang dapat kita sombongkan di hadapan Takdir dan Ida Sang Hyang Widi Wasa?