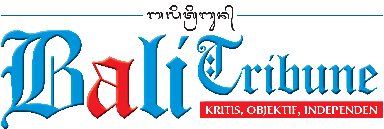balitribune.co.id | Belakangan ini di Bali muncul ada Desa Adat yang melakukan pungutan (pecingkreman) kepada masyarakat baik masyarakat asli maupun pendatang yang besaran/nominalnya ditentukan serta Objek Wajib Pecingkreman Desa (OWPD) juga ditentukan berdasarkan Keputusan Bendesa Adat. Sehingga banyak kalangan mempertanyakan apakah pungutan (pecingkreman) tersebut dibenarkan? Apakah pecingkreman seperti itu dapat dikatagorikan pungutan liar? Sebelum menjawab hal tersebut penulis akan menggali alasan kenapa Desa Adat melakukan pungutan yang nominalnya ditentukan dan objek/sasarannya juga ditentukan, serta dituangkan dalam sebuah Keputusan Bendesa Adat dan mereka menganggap hal tersebut sebagai dasar sah melakukan pungutan.
Alasan Pertama, adanya pengakuan eksistensi Desa Adat dalam undang-undang yang memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunana desa serta mendapatkan fasilitas dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota, sehingga perlakukan sama diberikan kepada Desa dan Desa Adat (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). Alasan kedua, Desa Adat sebagai subjek hukum dalam pemerintahan Provinsi Bali yang kedudukannya diakui untuk memajukan adat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal masyarakat Desa Adat (Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali). Selain kedua alasan tersebut diatas, yang digunakan sebagai dasar pungutan (pecingkreman) Desa Adat di Bali adalah Awig-Awig Uger-Uger, Keputusan Majelis Utama Desa Pekraman, Keputusan Pesamuan Agung, Perarem Desa Adat (aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig), dan lain-lain.
Tidaklah menjadi sebuah permasalahan jika pungutan (pecingkreman) menyasar masyarakat adat karena itu adalah sebuah kewajiban masyarakat adat dalam beryadnya, namun akan bersinggungan jika pungutan (pecingkreman) ini ditentukan Objek Wajib Pecingkreman Desa (OWPD) hingga menyentuh masyarakat tamiu (para pendatang) dan bahkan menyentuh bidang-bidang usaha/jasa yang ada di lingkungan Desa Adat tersebut. Pungutan (pecingkreman) yang diambil oleh Desa Adat dengan menentukan objek, besaran dan dilakukan secara berkelanjutan, menurut penulis adalah tidak patut dilaksanakan dan tidak dibenarkan. Walapun Desa Adat beralasan pungutan (pecingkreman) tersebut adalah hasil dari Awig-Awig, hasil Paruman Desa Adat, Uger-Uger, Keputusan Pesamuan dan lain-lain, tetap saja hal tersebut tidak dibenarkan. Kenapa demikian? Kita kembali kepada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana dalam penjelasannya disebutkan Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan Asas “lex superior derogat legi inferiori”, dimana aturan hukum yang kedudukannya lebih tinggi menghapus hukum yang kedudukannya lebih rendah, atau dengan kata lain hukum yang lebih rendah tingkatannya harus sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi. Hirarki peraturan ini terkonsep dari karya Hans Kelsen yang mencerminkan sistem hukum dari sudut pandang dinamis, yang lebih dikenal dengan Teori Stufenbau dimana ia menyebutkan “hubungan antara tingkat yang lebih tinggi dan lebih rendah dari sistem hukum - seperti antara konstitusi dan undang-undang, atau antara keputusan undang-undang dan peradilan, adalah hubungan menentukan atau mengikat - Dalam mengatur penciptaan norma ditingkat bawah, norma yang lebih tinggi sangat menentukan, tidak hanya pada proses bagaimana norma tingkat bawah dibuat, tetapi juga pada isi norma yang akan dibuat” (Kelsen 1992: §33, 77-78 – Stanley L. Paulson,
https://journals.openedition.org/revus/2727). Artinya norma hukum itu sifatnya berjenjang memiliki hirearki tata susunan. Sehingga hukum yang paling rendah harus bepegangan pada norma hukum yang lebih tinggi dalam hal ini yang diperhatikan adalah hierarkhi peraturan perundang-undangan, misalnya ketika terjadi pertentangan antara Peraturan Daerah dengan Undang-Undang, maka yang digunakan adalah Undang-Undang karena Undang-Undang lebih tinggi derajatnya, atau tidak boleh ada pertentangan antara produk hukum adat berupa Awig-Awig, Hasil Paruman Desa Adat (perarem), Uger-Uger, Keputusan Majelis Utama Desa Pekraman, Keputusan Pesamuan Agung dan lain-lain dengan Peraturan Daerah (sebagai representasi hukum positif) yang sifatnya nasional. Sehingga secara materi / isi dari Awig-Awig, Hasil Paruman Desa Adat (perarem), Uger-Uger, Keputusan Pesamuan dan lain-lain yang merupakan hasil produk hukum Desa Adat tidak boleh bertentangan dengan Hukum Positif (Peraturan Perundang-Undangan).
Di Indonesia dikenal adanya pajak dan pungutan, hal itu diatur dalam ketentuan Pasal 23 A UUD 1945 disebutkan pajak dan pungutan lain yang sifat memaksa diatur dengan undang-undang. Jadi sangat jelas konstitusi negara kita menyebutkan bahwa pungutan yang sifatnya memaksa harus berdasarkan pada undang-undang. Hefting atau pungutan adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang dan gunanya untuk membiayai kepentingan umum, yang terdiri dari : (1) Pajak – sifatnya dipaksakan dan dalam pemungutan pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi/balas jasa secara langsung; (2) Retribusi - dapat dipaksakan secara ekonomis, namun ada jasa timbal balik secara langsung kepada para pembayar retribusi; dan (3) Iuran/sumbangan – dapat dipaksakan secara ekonomis dan tidak ada jasa timbal balik secara langsung; Lebih lanjut aturan tentang Pungutan / pengumpulan uang sebenarnya telah diatur dalam UU No. 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang, dan tetap prosedur pengumpulan uang (pungutan) sah dilakukan jika mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota;
Kembali kepada permasalahan, apakah Desa/Desa Adat berwenang melakukan pungutan yang sifatnya memaksa? Memang tidak ada larangan Bendesa Adat membuat sebuah Keputusan untuk memungut (pecingkreman) kepada krama desa adat baik krama asli maupun krama pendatang serta pungutan terhadap usaha-usaha di wilayah Desa Adat yang besarannya ditentukan dan bersifat berkelanjutan, hanya saja permasalahan akan muncul dalam hal penerapannya dilapangan. Ada saatnya Hukum Pidana akan memainkan perannya, kapan itu?, yaitu saat petugas pungut (petugas adat) melakukan pungutan dengan cara memaksa atau sifatnya memaksa. Disaat ada warga yang keberatan untuk membayar pungutan (pecingkreman), dan tetap dipaksa oleh petugas pungut maka disinilah tindak pidana terjadi. Dan jika sampai korban melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib maka disinilah Tim Saber Pungli akan memainkan perannya.
Apabila kita kembalikan ke dalam konsep keberlakuan hukum tentu saja efektivitas keberlakuannya sangat dipengaruhi dari adanya satu kesadaran hukum dari masyarakatnya serta adanya sanksi yang dijadikan oleh masyarakat sebagai patokan dalam berperilaku. Dalam konteks hukum adat efektivitas keberlakuan sanksi yang diterapkan hukum adat tidak dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Mengapa itu bisa terjadi?, karena daya ikat hukum adat hanya sebatas pada Krama Adat atau warganya saja. Sanksi hukum adat tersebut tidak dapat dipaksakan kepada krama di luar masyarakat hukum adat itu sendiri, contoh : jika kita melihat sanksi hukum adat yang paling berat dapat dijatuhkan antara lain seperti : “kesepekang” atau misal tidak mendapatkan pelayanan adat pada saat nunas Tirta maupun pengabenan. Apakah sanksi demikian juga akan berlaku efektif kepada warga pendatang? (termasuk juga yang non Hindu). Tentu saja tidak, sehingga apabila sanksi hukum adat dipaksakan kepada krama pendatang hal tersebut tidak akan dipatuhi dan tidak dapat mengikatnya, untuk itu yang dapat dilakukan oleh Desa Adat jika ingin memperluas sebuah peraturan atau peraturan adat ialah dengan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat (diwewidangannya) baik krama asli mapun krama tamiu/pendatang (termasuk warga non Hindu) untuk bersama-sama ikut membangun Desa Adat dengan sumbangsih dan kesukarelaan sesuai dengan kemampuannya. Itulah yang menjadi penekanan, bahwa keberlakuan hukum adat dan segala perangkat peraturan yang disusun oleh adat hanya bisa berlaku secara efektif apabila dibarengi kesadaran hukumnya masyarakatnya. Hukum dipatuhi karena ada sanksi yang memaksa, dan walaupun sudah ada sanksi, pelanggaran hukum tetap saja terjadi. Sehingga keberlakuan hukum yang efektif sesunguhnya bukan pada sanksi, tapi pada kesadaran hukum bersama yang harus dibangun dengan pendekatan sosial, yang humanis dan melalui penyuluhan-penyuluhan (Dewa Arya Lanang Raharja – Praktisi Hukum, 24/01/2020).
Kembali pada Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali, sudah jelas dinyatakan bahwa Desa Adat dimungkinkan sah untuk memungut pungutan (pecingkreman) kepada warga tamiu (pendatang) berbentuk hibah dan sumbangan (dana punia) sifatnya sukarela. Artinya pungutan (pecingkreman) yang dilakukan oleh desa adat sifatnya tidak boleh memaksa dan tidak ditentukan jumlahnya serta tidak bersifat berkelanjutan (periodik). Jadi tidak ada alasan pembenar pungutan bebas dilakukan dikarenakan Desa Adat kekurangan dana dalam menjaga adat-istiadat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal yang menjadi sumber nilai-nilai tata kehidupan Bali. Hal ini dikarenakan Desa Adat di Bali telah memiliki sumber pendapatan Desa Adat yang disebut Anggaran Pendapatan Desa Adat yang bersumber dari : (a) Pendapatan Asli Desa Adat; (b) Hasil Pengelolaan Padruwen Desa Adat; (c) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; (d) Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota; (e) Bantuan Pemerintah Pusat; (f) Hibah dan Sumbangan (Dana Punia) pihak ketiga yang tidak mengikat; dan (g) Pendapatan lain-lain Desa Adat yang sah (Pasal 65 Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali). Sumber pendapatan Desa Adat inilah yang seharusnya dimaksimalkan untuk menjaga adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang menjadi sumber nilai-nilai tata kehidupan Bali.
Penulis juga melihat memang beratnya menjaga adat istiadat, dimana Desa Adat adalah benteng terdepan menjaga budaya, adat istiadat dan bahkan termasuk berperan mejaga ketertiban bermasyarakat dan memberdayakan masyarakat Desa Adat. Untuk melaksanakan peran Desa Adat ini memang dibutuhkan anggaran yang besar dan dijaman sekarang ini Desa Adat tidak akan mampu jika hanya mengandalkan Pendapatan Asli Desa dari hasil Pengelolaan Padruwen Desa Adat atau dari Pendapatan lain-lain Desa Adat yang sah. Disini perlu dipikirkan oleh pemerintah bahwa untuk menjaga kelestarian adat istiadat dan budaya maka harusnya salah satu pendapatan Desa Adat dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat harus ditingkatkan jumlahnya. Porsi anggaran untuk Desa Adat harus dinaikkan sehingga Desa Adat dapat menjalankan perannya menjaga dan membangun desa sesuai tujuan. Untuk itu Desa Adat tidak lagi melakukan kegiatan memungut dana dari masyarakatnya yang justru menjerumuskan perangkat desa adat keranah pelanggaran hukum.
Disisi lain desa Adat juga harus kreatif dalam mengembangkan Usaha Desa Adat yaitu Labda Pacingkreman Desa Adat (LPD – Lembaga Perkererdiatan Desa) dan Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPAD), saat Desa Adat berhasil mengembangkan usahanya maka tidak lagi diperlukan kegiatan pungut memungut dana dari masyarakat yang berpotensi terjadi pelanggaran hukum. Usaha inilah yang dikembangkan dengan melibatkan semua warga baik asli maupun pendatang. Mereka semua diajak berperan aktif mengembangkan usaha Desa Adat sehingga keuntungannya dapat membantu Desa Adat dari sisi materiil untuk membiayai penyelenggaraan program Desa Adat.