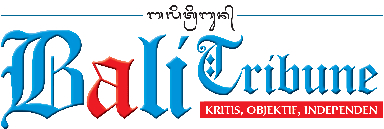balitribune.co.id | Denpasar - Fenomena "desakralisasi" terhadap tradisi sakral Bali terus menjadi persoalan, bak bola bergulir yang tak kunjung usai. Berbagai upaya dilakukan untuk mencari titik temu, hingga menjadi perbincangan hangat, baik di keluarga maupun kalangan ahli.
Puluhan orang yang terdiri dari para dosen, mahasiswa, bendesa adat, dan masyarakat berkumpul pada 'Seminar Seni Sakral' yang diadakan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali bersama Majelis Kebudayaan Bali, Selasa (2/8).
Kegiatan ini membahas kesenian sakral Bali yang pada intinya mencari pemecahan terhadap fenomena "desakralisasi" yang selama ini terjadi. Perbincangan yang berlangsung kurang lebih 3 jam ini berlangsung di Gedung Citta Kelangen, Institut Seni Indonesia, Denpasar.
Narasumber pertama yakni, Dr Drs I Gusti Ngurah Seramasara Mhum, menyampaikan topik terkait seni pertunjukan sakral, proses dan pementasannya dalam masyarakat Hindu Bali. Ia mengawali dengan penjelasan bahwa masyarakat Bali mewarisi seni pertunjukan seni, wayang, dan gamelan, terkait dengan upacara keagamaan.
Dimana, proses dan pementasannya memiliki keunikan tersendiri, sesuai dengan kebiasaan lokal (kuna dresta, loka dresta) yang kemudian dikenal dengan desa kala patra. Seni pertunjukan ini hanya dilakukan pada saat ada upacara keagamaan.
Ternyata keunikan itu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Pada masa penjajahan atau awal abad 20, kebijakan kolonial menjadikan Bali sebagai daerah wisata. Darisitu mulailah terjadi komodifikasi seni pertunjukan sakral. Seperti pada 1930, "cak" yang merupakan pengiring tari Sanghyang, dikemas menjadi pertunjukan tari Kecak, dengan memasukan cerita Ramayana.
Itu sebabnya, Kecak kemasan ini menjadi daya tarik wisata hingga menyebar seperti ke Bona, Kemenuh, Singapadu, Sumerta dan seterusnya. Sehingga berlanjut menjadi pertunjukan yang dipertontonkan untuk para wisatawan.
Dengan berkembanganya pariwisata Bali saat itu, suasana sosial budaya dan sosial religius berpengaruh pada fungsi seni pertunjukan. Sehingga mengaburkan persepsi akan seni sakral yang hanya dipentaskan saat upacara dan seni pertunjukan yang berorientasikan uang.
Walau demikian, kata Ngurah pada dasarnya masyarakat Bali tidak mengenal istilah sakral maupun sekuler. Hanya saja 'orang Bali' memaknainya sebagai kepercayaan, proses ritual, angker, suci, dan waktu tertentu, bukan pemisahan terhadap ruang.
Proses tari sakral yang dapat diamati di Bali, ada yang diwarisi dan ada juga yang merupakan hasil kreativitas. Maka dari situasi tersebut berkembanglah proses sakralisasi dan sekulerisasi dalam masyarakat Bali.
Selanjutnya proses sakral tersebut ditetapkan berdasarkan lontar dalam ajaran Hindu Bali. Oleh karena itu, tidak sembarang ciptaan dapat dijadikan tari sakral. Saat ini, banyak sekali ciptaan seni yang dikaitkan dengan upacara keagamaan tetapi juga dipentaskan di sembarang tempat, yang mempertajam kekaburan seni sakral masyarakat Bali.
"Misalnya seperti fenomena Rejang Renteng sebagai seni upacara, apakah sudah direkonstruksi melalui proses sakral? bila sudah mengapa dipentaskan juga di sembarang tempat?, hal seperti ini yang perlu diluruskan," kata Ngurah.
Ia menambahkan, jika sesungguhnya kesenian khususnya tarian sakral tidak bisa dipertunjukan secara massal, seperti maraknya fenomena saat ini. Karena sifatnya yang sakral dan terikat dengan upacara. Namun bukan sakral yang terikat dengan ruang (tempat), karena menurutnya ruang di Bali tidak ada yang tidak sakral.
Sepakat dengan pernyataan itu, narasumber kedua, Prof Dr I Nengah Duija Msi menyebutkan, ketika seni menjadi tontonan massal, maka nilai seninya menjadi hilang. Seperti halnya kekeliruan terhadap seni sakral di Bali.
Misalnya pada seni calonarang, yang sesungguhnya merupakan pertentangan dua sifat baik dan buruk (barong dan rangda), tapi tidak ada yang kalah. Namun, fenomena sekarang justru masyarakat berpaling perhatian pada "sawa" atau bangke matah.
Terkait fenomena desakralisasi, Duija berpendapat, untuk pihak manapun khususnya pemerintah janganlah seni sakral dijadikan momen yang diperjual belikan untuk pariwisata. Pada momen itu Ia juga menyampaikan, Majelis Kebudayaan Bali (MKB) memiliki kewajiban untuk membuat pedoman-pedoman yang mengatur tentang hal ini.
"Hasil seminar ini bisa menjadi panduan untuk menyusun kebijakan, dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek, pemajuan tradisi budaya," ujarnya.