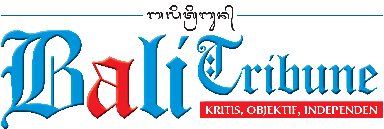balitribune.co.id | Pasal 39 ayat (3) UU LKM bukanlah dasar hukum pembentukan LPD, Lumbung Pitih Nagari, atau lembaga lain sejenis yang dibentuk berdasarkan hukum adat. Dasar hukum pembentukan LPD, Lumbung Pitih Nagari, dan lembaga-lembaga sejenis lainnya ada pada atau diturunkan dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu pada hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat. Itu pun dibatasi oleh syarat “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.
Oleh karena itu, sekiranya di masa yang akan datang hendak didirikan lembaga-lembaga sejenis LPD, Lumbung Pitih Nagari berdasarkan hukum adat, hal itu sudah berada di luar konteks Pasal 39 ayat (3) UU LKM. Jika hal itu benar-benar menjadi kenyataan di masa yang akan datang maka, dengan bertolak dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, pembentukan lembaga-lembaga demikian adalah dibentuk oleh suatu kesatuan masyarakat hukum adat dan kesatuan masyarakat hukum adat itu terbukti (atau setidak-tidaknya dipraanggapkan) masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena, sesuatu yang sudah “mati” tidak mungkin melakukan perbuatan hukum.
Selanjutnya, dari perspektif ilmu perundang-undangan dan metode penafsiran kontekstual, catatan penting lain yang didapat dari rumusan norma dalam Pasal 39 ayat (3) UU LPM adalah bahwa “Lembaga Perkreditan Desa” ditulis dengan huruf kapital. Secara ilmu perundang-undangan maupun metode penafsiran kontekstual (contextual interpretation), hal itu bermakna bahwa istilah tersebut (“Lembaga Perkreditan Desa”) menunjuk nama diri, bukan nama generik, dalam hal ini istilah tersebut secara khusus dimaksudkan merujuk kepada nama lembaga perkreditan yang dibentuk berdasarkan Hukum Adat Bali.
Demikian pula halnya dengan Lumbung Pitih Nagari yang merujuk pada lembaga perkreditan yang dibentuk berdasarkan Hukum Adat Minangkabau (Sumatera Barat). Oleh karena itu, hukum yang berlaku terhadap LPD adalah Hukum Adat Bali. Penalaran yang sama juga berlaku terhadap Lumbung Pitih Nagari serta lembaga-lembaga lain sejenis yang dibentuk berdasarkan hukum adat sebelum UU LKM berlaku.
Masalahnya kemudian, sebagaimana halnya hukum adat di daerah lain, Hukum Adat Bali adalah hukum tidak tertulis dalam pengertian bukan hukum yang terkodifikasi (codified law) atau hukum positif (positive law). Sementara itu, meskipun bertolak dari asas-asas yang sama, Hukum Adat Bali dalam detailnya sangat terikat pada praktik/tradisi desa mawa cara (setiap tempat memiliki aturannya sendiri) sesuai dengan loka dresta (kebiasaan setempat) yang hidup di suatu Desa Pakraman. Dengan praktik demikian, asas Hukum Adat Bali yang sama dapat diejawantahkan dalam ugeran (aturan) dan praktik yang berbeda-beda di tiap-tiap Desa Pakraman. Misalnya, asas kepatutan bisa melahirkan ugeran (baik berupa larangan ataupun suruhan/keharusan) dan praktik yang berlainan antara satu Desa Pakraman dan Desa Pakraman lain. Konsekeuensi selanjutnya, “sanksi” yang dikenakan terhadap seseorang yang melanggar ugeran yang diturunkan dari asas kepatutan itu pun berlain-lainnya bentuknya. Oleh karena itu, secara de facto dalam praktik sehari-hari, masing-masing Desa Adat (Desa Pakraman) sesungguhnya memiliki “hukum adat”-nya sendiri yang otonom kendatipun diikat oleh atau bertolak dari asas-asas hukum yang sama.
Dengan demikian, dalam kaitannya dengan LPD, secara teori pada dasarnya masing-masing Desa Adat (Desa Pakraman) yang memiliki LPD itu mempunyai otonomi untuk mengatur hal-hal yang berkenaan dengan LPD-nya sesuai dengan praktik desa mawa cara yang berlaku di Desa Pakraman yang bersangkutan. Karena itu, secara teori pula, sangat mungkin terjadi perbedaan dalam pengorganisasian maupun pengelolaan LPD di masing-masing Desa Pakraman. Bahwa perbedaan demikian tidak tampak saat ini adalah karena, menurut pengamatan saya, dalam konteks LPD, masing-masing Desa Pakraman selama ini mau belajar dari dan mencontoh Desa Pakraman lain yang berhasil mengelola LPD-nya sehingga, “LPD telah berhasil memberikan kekuatan baru kepada desa pakraman, dan menyediakan akses jasa keuangan yang inklusif bagi setiap orang di desa adat” (seperti yang dikatakan oleh peneliti asing yang tertarik melakukan riset terhadap LPD sebagaimana dikutip di awal tulisan ini).
Dalam kaitan ini maka, menurut saya, sangat penting bagi seluruh Desa Adat (Desa Pakraman) yang ada di Bali yang memiliki LPD untuk membuat perarem (kesepakatan bersama) sehingga terdapat kesatuan pandangan dalam menyelesaikan masalah yang mungkin timbul di lapangan dalam pengoperasian LPD, baik yang bersifat manajerial maupun organisasional. Dalam mengisi perarem itu, karena intinya adalah kesepakatan bersama, tidak ada larangan untuk mengadopsi aturan atau regulasi yang ada dalam hukum positif yang mengatur lembaga keuangan semacam LPD, termasuk misalnya yang ada dalam UU LKM atau bahkan best practices yang terbukti berhasil diterapkan di negara lain (jika ada), dan kemudian dipadukan dengan asas-asas Hukum Adat Bali dan pengejawantahannya dalam praktik yang dinilai telah terbukti berjalan baik.
Dengan cara demikian, lebih-lebih dengan dukungan teknologi terkini, diharapkan LPD akan benar-benar dikelola secara profesional dan modern dengan tetap mempertahankan watak dasarnya yang berakar pada Hukum Adat Bali sehingga, dalam jangka panjang, tidak mustahil LPD dapat menjadi role model (contoh) pengembangan lembaga keuangan mikro berbasis kearifan lokal, bukan hanya bagi daerah-daerah lain di Indonesia tetapi juga bagi dunia.
Muncul pertanyaan, bolehkah pengaturan tentang LPD itu dituangkan ke dalam peraturan daerah, dalam hal ini Peraturan Daerah Provinsi? Saya berpendapat, boleh dengan catatan bahwa peraturan daerah tersebut bukan untuk mengambil alih kewenangan Desa Adat (Desa Pakraman) dalam pengelolaan LPD tetapi justru mengukuhkannya. Peraturan daerah tersebut akan lebih mudah disusun apabila terlebih dahulu Desa-Desa Pakraman yang mempunyai LPD telah memiliki perarem sebagaimana diuraikan di atas.
Peraturan daerah dimaksud akan lebih mudah disusun jika perarem sebagaimana disarankan di atas telah ada karena peraturan daerah itu tinggal mengadopsi atau mengambil-oper dari hal-hal yang telah diatur dalam perarem tersebut. Lebih dari itu, peraturan daerah dimaksud harus menjadi pelindung kemandirian LPD, yang dengan demikian sekaligus berarti pelindung terhadap kemandirian Desa Pakraman, dari rongrongan pihak luar, termasuk dari pemerintah daerah sendiri (baik provinsi maupun kabupaten/kota). Dengan mengadopsi perarem demikian, pemerintah daerah dan Desa Pakraman akan memiliki cara pandang serta pegangan yang sama dalam memandang dan memperlakukan LPD. Hal ini juga akan memudahkan assessment terhadap praktik penyelenggaraan LPD, baik secara organisasional maupun majerial.
Pertanyaan lainnya, dalam hubungannya dengan Bali, oleh karena di Bali disamping ada Desa Adat (Desa Pakraman) juga terdapat Desa Dinas, bagaimana jika Desa Dinas juga membentuk lembaga serupa dengan nama serupa? Hal itu dapat saja terjadi jika pembentukannya dimungkinkan berdasarkan undang-undang, misalnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah atau Undang-Undang tentang Desa. Namun, jika lembaga demikian terbentuk, keberadaannya telah berada di luar pengaturan (pengecualian) Pasal 39 ayat (3) UU LKM. Sebab, Desa Dinas bukan kesatuan masyarakat hukum adat melainkan bagian dari penyelenggara pemerintahan sehingga ia sepenuhnya tunduk pada ketentuan hukum positif yang dibuat oleh negara, khususnya dalam hal ini Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang Desa. Dengan demikian, karena bergerak di bidang keuangan mikro dan bukan dibentuk berdasarkan hukum adat, maka lembaga yang disebut terakhir ini (jika ada) tunduk pada UU LKM. Sebaliknya, Desat Adat (Desa Pakraman) pun tidak boleh turut campur terhadap lembaga ini meskipun, misalnya, lembaga tersebut berada dalam wilayah (wewengkon atau wewidangan)-nya secara adat.
Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. (habis)